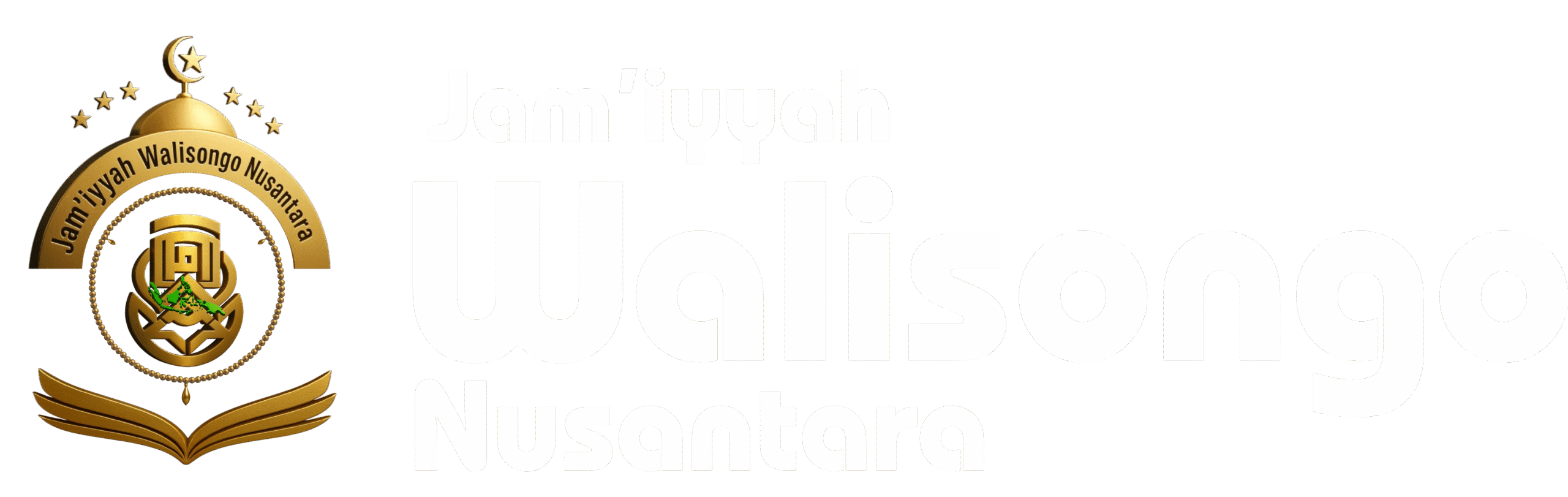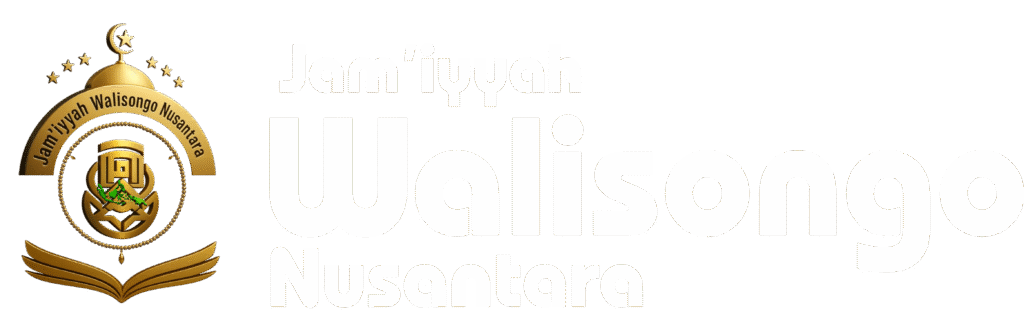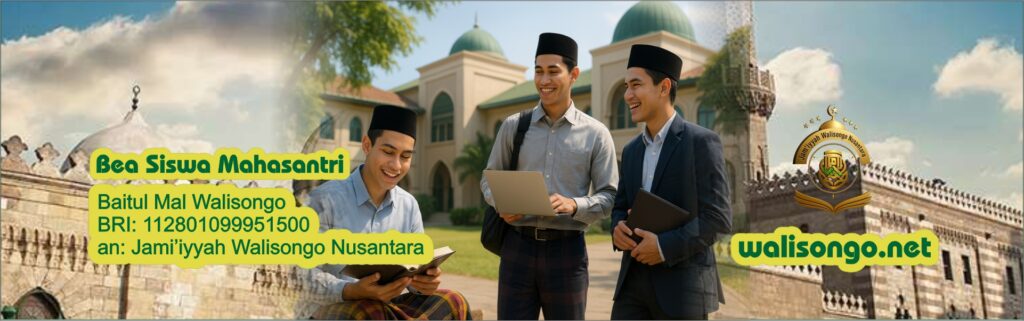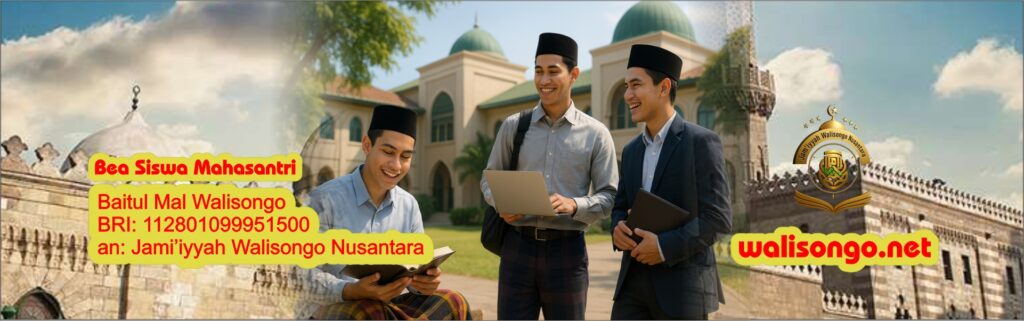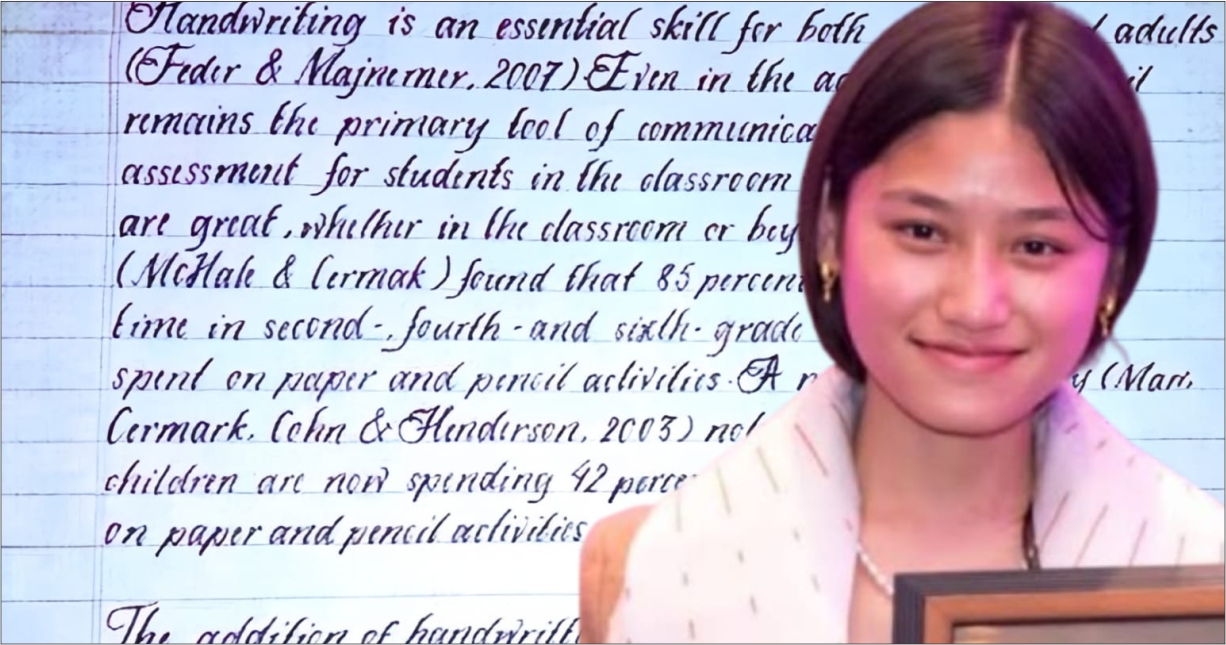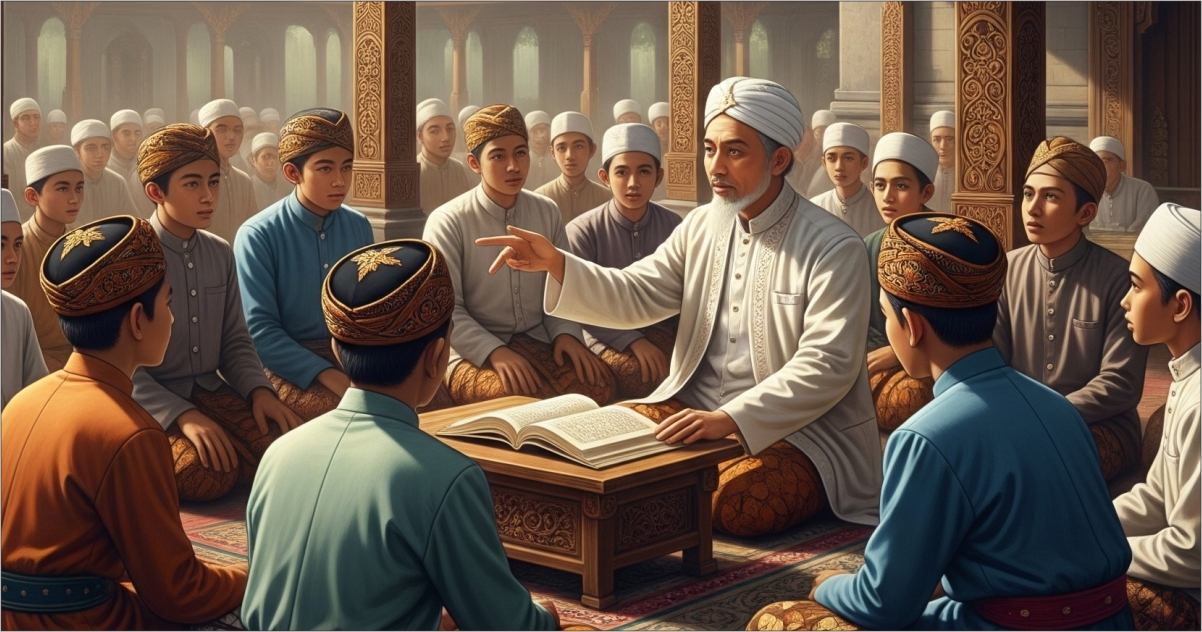Selama ini dunia disuguhi pemandangan dramatis tentang langit yang terbelah oleh rudal-rudal Iran. Seolah-olah rezim Mullah itu hanya jagoan udara —dengan peluncur rudal hipersonik, drone kamikaze yang menghantam pertahanan Israel, serta parade ayatollah yang tampak seperti cosplay insinyur pertahanan.
Namun, jangan hanya terpukau oleh pameran langit ini, karena di bawah permukaan laut, diam-diam Iran sedang membangun sebuah simfoni kekuatan laut yang dahsyat. Bahkan tak semua orang Indonesia —pemilik semboyan laut gagah berani Jalesveva Jayamahe— menyadari irama nadanya.
Jika baru saja parlemen Iran sepakat menutup Selat Hormuz, itu karena armada laut mereka siap membendung. Keputusan dan tindakan Iran ini tidak sekadar mencerminkan keberanian strategis, tetapi juga mengirimkan sinyal global yang sangat jelas: jangan main-main dengan negeri Mullah yang punya kapal selam di setiap bisikan sonar.
Selat selebar hanya 33 kilometer ini memang kecil secara geografis, tapi besar secara geopolitik. Bayangkan, sepertiga minyak dunia melintas melalui jalur air ini setiap harinya. Di sini, satu torpedo bisa membuat harga minyak melonjak, satu kapal tanker bisa membuat pasar dunia gemetar.
Bayangkan juga jika Indonesia punya Selat Hormuz-nya sendiri. Atau, lebih tepatnya, bayangkan kalau kita sadar bahwa sebenarnya kita memang punya ratusan “Selat Hormuz mini” di perairan sendiri. Laut Arafura, Selat Malaka, Selat Makassar, Laut Natuna —semuanya jalur strategis global, tempat lalu lintas dagang dan energi dunia bergerak.
Tapi bedanya, ketika Iran bisa “mengunci” selat kecilnya dengan pasukan laut siap tempur, Indonesia masih berkutat dengan perdebatan anggaran solar dan kapal nelayan asing yang mondar-mandir seperti tetangga tak tahu malu. Keberhasilan mencegat kapal-kapal ini tak jarang diekspos seolah karya maha hebat.
Iran memang bukan kekuatan maritim dalam gaya konvensional ala Amerika Serikat yang bisa mengirim kapal induk ke depan gerbang musuh sambil memutar lagu kebangsaan. Tapi Iran paham satu hal penting: jika Anda tidak bisa mengalahkan armada besar, jadilah momok kecil yang terus menggigit dan tak bisa dipukul.
Dengan lebih dari seratus kapal perang dan 18.500 personel, kekuatan laut Iran —dibagi antara Angkatan Laut reguler (IRIN) dan Armada Pengawal Revolusi (IRGCN)— lebih mirip perpaduan antara warisan kolonial dan kreativitas lokal.
Dalam jajarannya ada kapal perusak modern seperti Sahand dan Zulfiqar, kapal frigat Moj-class. Dan —ini favorit para tukang sabotase laut— mini-submarin Ghadir yang cukup lincah untuk menari-nari di perairan dangkal sambil membawa kejutan torpedo.

Sebagai bonus, mereka juga memiliki kapal selam Fateh dan Thariq yang meskipun sudah uzur, tetap mampu menabur ranjau dan mengintip diam-diam dari balik kegelapan laut.
Belum cukup? Silakan sambut Nahang-class, kapal selam tunggal spesialis penyusupan pasukan khusus. Kalau Anda merasa ini seperti plot film spionase murahan, maka selamat —Anda memahami cara kerja militer Iran.
Iran tahu, kekuatan tidak hanya datang dari kapal, tapi dari tempat kapal itu beranak-pinak dan bertelur. Mereka sadar, inilah fondasi kekuatan mereka. Maka dari itu, mereka menyebar pangkalan militer di sepanjang Laut Kaspia, Teluk Persia, dan Samudra Hindia.
Bandar Abbas adalah mall-nya kapal perang, lengkap dengan fasilitas produksi kapal dan kapal selam.
Jask adalah pos pengamatan yang secara tak langsung bisa mengintip kapal dagang yang lewat di Selat Hormuz.
Chabahar? Anggap saja pelabuhan ini sebagai pintu belakang Iran menuju Asia Tengah.
Abu Musa, pulau penuh konflik dengan UEA, dijadikan basis rudal dan bunker bawah tanah. Kalau Indonesia saja punya konflik dengan Malaysia soal Ambalat, Iran memilih cara lebih macho: tanam rudal di Abu Musa, pulau sengketa.
Kini mari kita kembali ke negeri maritim bernama Indonesia. Negeri yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan laut yang luasnya seperti perasaan mantan yang belum move on, tapi ironisnya punya angkatan laut yang lebih sering berurusan dengan illegal fishing daripada perang laut.
Kita bangga dengan semboyan “Jalesveva Jayamahe”, yang menurut tafsir nasionalis artinya “Justru di laut kita menang.” Tapi jika dibaca secara literal —”di laut kita sedang menang”— rasanya seperti doa yang belum terkabul.
Kapal perang kita kadang kalah cepat dibanding influencer naik jetski, dan jumlah kapal selam kita lebih sedikit dari jumlah stasiun TV swasta. Jadi jelas, Iran membangun; kita tak maju-maju, selalu menunggu anggaran yang tak selesai-selesai dikorupsi.
Pada tahun 2024, Iran memperkuat armadanya dengan lebih dari 2.600 sistem rudal dan drone. Bahkan mereka menguji coba peluncuran rudal jelajah dari kapal selam kecil. Seolah mereka tak pernah lelah mengeksplorasi kemungkinan dari sumber daya yang minimal.
Mereka juga sudah membayangkan kapal selam bertenaga nuklir, walau realisasinya masih terhambat sanksi dan kekurangan uranium yang tidak dipakai untuk pesta. Nuklir di Iran ternyata dibuat untuk tenaga kapal, bukan untuk memusnahkan lawan.
Bandingkan dengan kita yang masih ribut soal KRI Nanggala dan proyek Frigate Merah Putih yang berlayar di atas ketidakpastian anggaran. Bukan hanya tidak pasti—sebab anggaran sebetulnya bisa disisihkan jika tidak habis disedot korupsi.
Iran bahkan mengirim kapal Dana dan Makran keliling dunia hingga mencapai Selat Magellan sejauh 63.000 kilometer. Indonesia? Kita masih berdebat siapa yang bertanggung jawab atas anggaran solar untuk kapal patroli yang mogok di Laut Natuna.
Tentu kita tidak sedang menyarankan Indonesia meniru Iran secara ideologis atau strategis. Tapi mari kita belajar satu hal dari negeri para mullah ini: ketika Anda dikepung embargo, diancam setiap minggu, dan dibenci separuh dunia, kekuatan maritim bukanlah pilihan, tapi kebutuhan.
Iran membuktikan bahwa kekuatan laut bukan soal siapa paling besar atau paling mahal, tapi siapa yang paling siap dalam kondisi terburuk. Laut bukanlah sekadar batas wilayah; ia adalah pusat ekonomi, arteri energi dunia, dan—bagi Iran—bahkan panggung propaganda.
Sementara itu, Indonesia yang hidup dalam damai, dengan kekayaan laut luar biasa, dari terumbu karang hingga cadangan energi dan perikanan, justru belum menempatkan angkatan laut sebagai garda utama. Bangga sebagai negeri maritim, tapi baru sampai di lidah saja.
Mungkin, sudah saatnya semboyan Jalesveva Jayamahe benar-benar dimaknai: bukan sebagai kenangan kejayaan Majapahit yang tak pernah kita lihat, tapi sebagai komitmen strategis yang bisa kita bangun—di atas kapal, di dalam laut, dan lewat visi pertahanan yang tidak lagi mengandalkan doa saja.
Jika Iran bisa menjaga Laut Oman sambil memamerkan rudal di langit Damaskus, masa kita tidak bisa menjaga Laut Natuna sambil memperbaiki mesin kapal patroli? Mungkin jawabannya bukan pada kekuatan laut kita, tapi pada keberanian untuk tidak hanya berlayar, melainkan juga berpikir.
Masih yakin Jalesveva Jayamahe? Tentu. Tapi mari mulai dengan memastikan kita punya kapal yang cukup dulu.