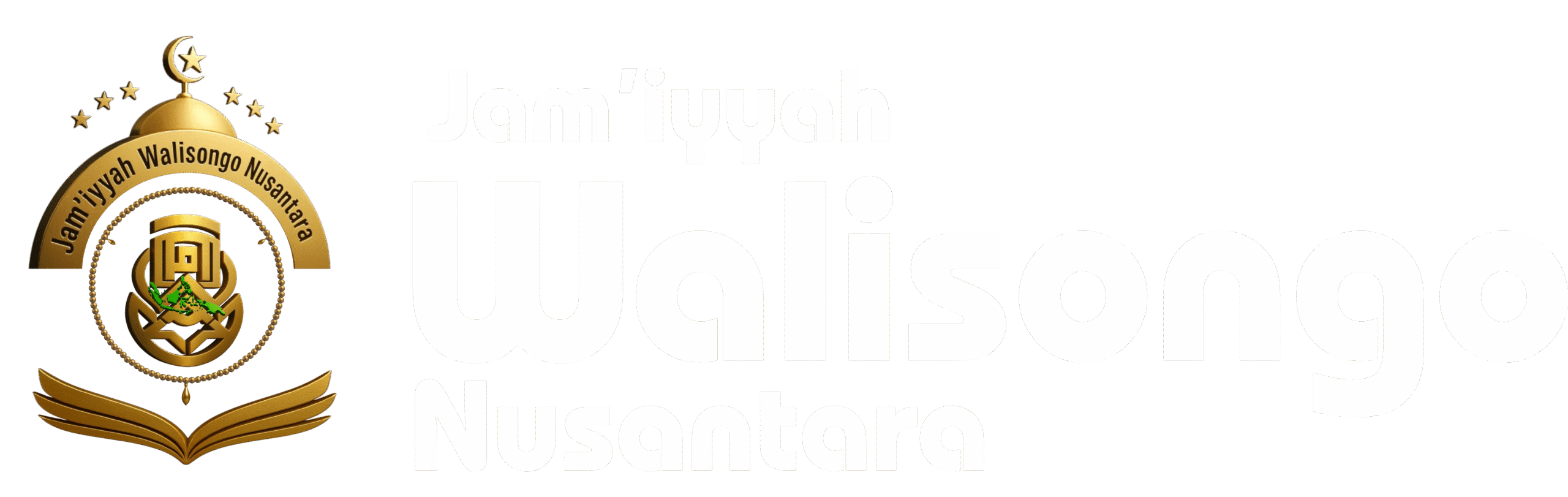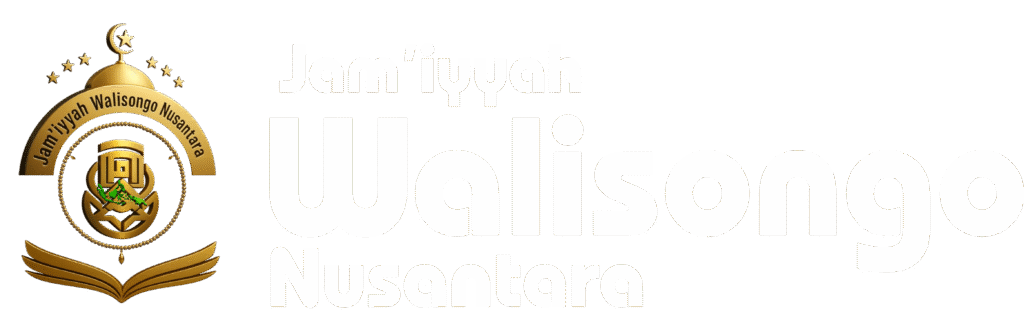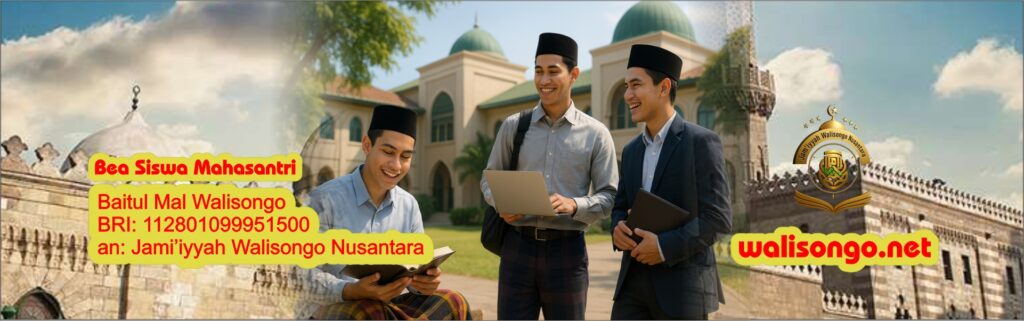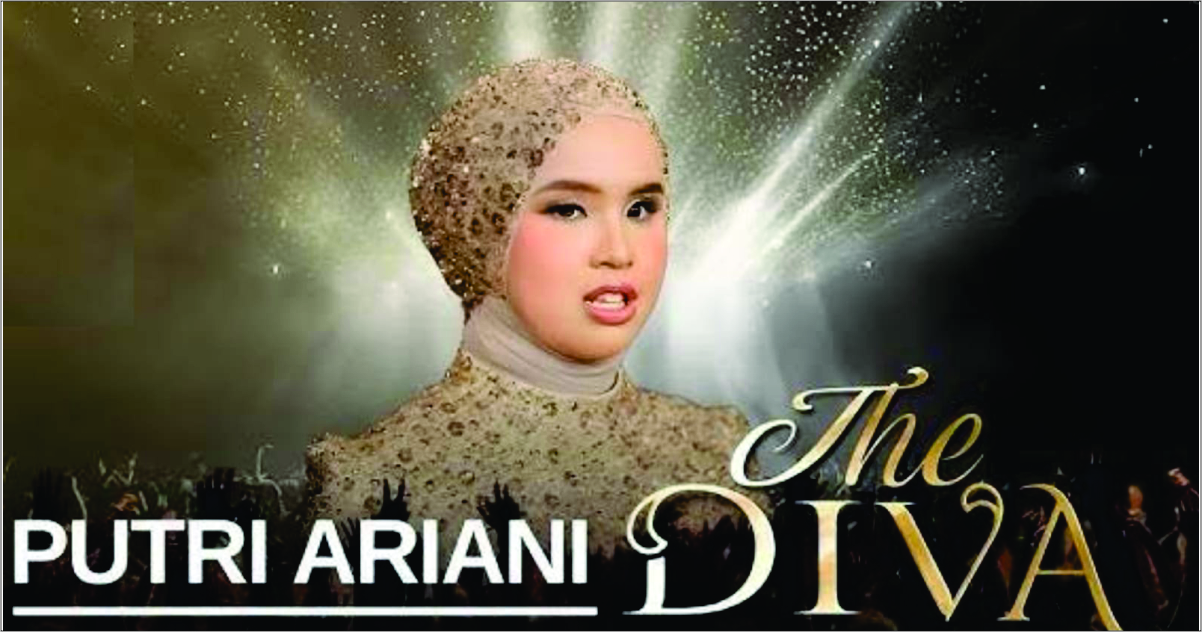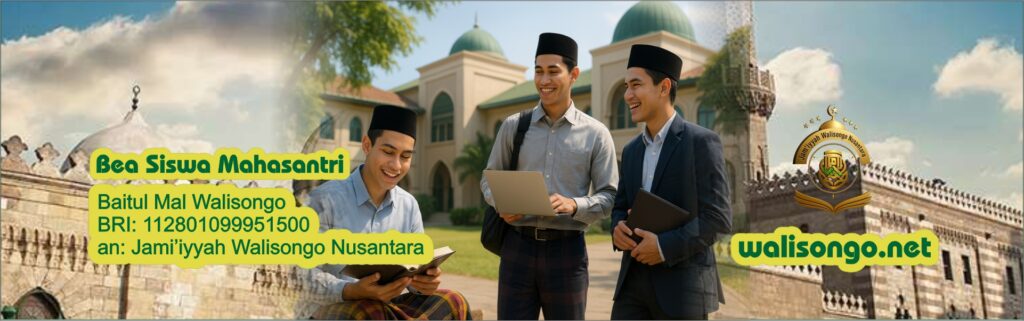Dituduh pemberontak, padahal ia yang memasak semangat republik di dapur kemerdekaan. Daud Beureueh bukan durhaka. Dia hanya kecewa karena dapurnya diobrak-abrik pusat.
Konon, sejarah ditulis oleh para pemenang. Tapi di negeri ini, yang kalah pun sering menulis ulang sejarah —asal dapat restu politik. Maka jangan heran kalau suatu saat tokoh yang dicap “pemberontak” bisa berubah jadi “pahlawan nasional”.
Syaratnya, asalkan framing-nya cocok dan nuansanya tidak mengganggu stabilitas politik terbaru. Dan kalau ada satu nama yang patut dijemput kembali dari pojok sejarah yang berdebu, itu adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh.
Lho, bukankah dia pemimpin pemberontakan DI/TII Aceh? Tunggu dulu. Jangan buru-buru mencelupkan orang ke dalam tinta hitam sejarah tanpa mengecap dulu rasanya: pahit kecewa, asin dikhianati, pedas karena janji pusat yang dibakar angin.
Daud Beureueh itu —kalau boleh jujur— adalah seorang nasionalis yang lebih republiken daripada banyak yang hari ini memelintir republik demi tender. Ia bukan ulama yang mendadak angkat senjata karena lapar kekuasaan.
Sungguh, dia seorang pejuang yang sudah melawan Jepang dan membabat Belanda. Dialah yang berseru lantang menyambut proklamasi 1945, saat sebagian tokoh Aceh masih bimbang antara mau merdeka sendiri atau lanjut jadi protektorat kolonial.
Maka ketika Bung Karno datang ke Aceh tahun 1946 dan Daud Beureueh menyodorkan permintaan agar Aceh dijadikan provinsi dengan keistimewaannya, Bung Karno setuju. Bahkan, tak main-main: beliau diangkat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dengan pangkat tituler Mayor Jenderal.
Kalau mau disebut pemberontak, logikanya bisa ditarik mundur ke Bung Karno juga. Tapi tentu itu absurd. Yang sesungguhnya terjadi adalah janji-janji pusat yang kerap berubah warna seperti bunglon kena pancaran sorot politik Jakarta.
Kisahnya mirip drama sinetron epik: pada 1950, status Aceh sebagai provinsi dicabut secara sepihak oleh pusat. Daud Beureueh kecewa, tapi tetap sabar. Ketika Natsir datang membujuk, dia berkata, “Nasi sudah jadi bubur.” Tapi bubur yang dimaksud bukan menu sarapan biasa. Ini bubur politik, disajikan dingin, tanpa topping keadilan.
Lalu Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) meletup. Tahun 1953, Daud menyatakan perlawanan terbuka terhadap pusat. Tapi siapa yang memulai provokasi? Apakah yang mengangkat senjata lebih bersalah dari yang mengingkari perjanjian?
Sebagaimana disampaikan Yusril Ihza Mahendra dalam seminar nasional terbaru di Banda Aceh, akar dari semua ini bukan semangat separatisme, melainkan kekecewaan terhadap pusat. Kalau negara ini punya hati, mestinya bisa merasakan luka lama itu.
Daud Beureueh bukan hanya Gubernur. Ia ulama kharismatik, pemimpin yang dihormati rakyat Aceh. Sejarawan seperti Anthony Reid hingga George McTurnan Kahin mencatat bahwa Daud adalah bagian penting dari dinamika pembentukan republik di daerah.
Ia ikut membentuk struktur pemerintahan sipil dan militer di Aceh yang menopang eksistensi RI di masa-masa genting. Kalau ini yang disebut pemberontakan, maka republik ini lahir dari pemberontakan juga: terhadap penjajahan, terhadap ketidakadilan, terhadap dominasi pusat atas daerah.
Dalam banyak buku sejarah versi resmi negara —termasuk kurikulum sekolah— DI/TII hampir selalu dicatat sebagai pemberontakan bersenjata terhadap Republik Indonesia. Tak hanya di Aceh, tapi di sejumlah daerah.
Nama-nama seperti Kartosuwiryo menggerakkan DI/TII di Jawa Barat, Kahar Muzakkar di Sulawesi, dan Daud Beureueh di Aceh. Dalam buku sejarah, mereka dimasukkan dalam satu kotak hitam bernama “separatisme Islam.”
Narasi ini muncul kuat terutama pada era Orde Baru, yang secara sistematis membungkus segala bentuk ketidakpuasan daerah terhadap pusat sebagai ancaman terhadap kesatuan nasional. Stigma pemberontakan dilekatkan pada mereka.
Padahal, banyak sejarawan kritis seperti Prof. Djajadiningrat atau bahkan pengamat luar negeri seperti Harold Crouch mencatat bahwa gerakan DI/TII bukanlah semata ekspresi separatisme ideologis.
Menurut mereka, gerakan itu merupakan reaksi terhadap pengingkaran janji politik, marginalisasi daerah, dan kekecewaan terhadap pemerintahan pusat.
Dalam kasus Aceh, keterlibatan Daud Beureueh dalam DI/TII lebih tepat dibaca sebagai upaya mempertahankan martabat dan konsistensi terhadap cita-cita awal perjuangan kemerdekaan. Itu bukan semangat untuk membelah republik.
Yusril benar: sejarah Daud Beureueh perlu ditulis ulang. Seperti Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara, yang dulu sempat dicap pemberontak karena bergabung dengan PRRI, kini mereka sudah direhabilitasi dan diberi gelar Pahlawan Nasional. Padahal perjuangan mereka juga karena rasa kecewa terhadap praktik kekuasaan yang menelikung nilai-nilai demokrasi.

Daud Beureueh bahkan tidak pernah menyatakan niat memisahkan Aceh dari Indonesia. Ia hanya ingin janji ditepati, martabat dihargai, dan Aceh diberi tempat yang layak sebagai provinsi yang berjasa menyelamatkan republik di awal kemerdekaan.
Akhirul kalam, sejarah bukan luka yang perlu disembunyikan dengan balsem narasi penguasa. Ia, seperti seharusnya ditulis ulang oleh Menteri Kebudayaan, harus disorot terang-terangan, dibaca dengan utuh, dan diakui apa adanya.
Kalau benar republik ini berdiri atas dasar kejujuran dan keadilan, maka sudah waktunya Daud Beureueh dibebaskan dari stigma pemberontakan dan dikenang sebagaimana mestinya: sebagai pahlawan yang terluka, tapi tidak pernah lari dari semangat republik.
Toh hari ini, banyak yang lebih parah dari pemberontak, tapi dielu-elukan sebagai negarawan —asal modalnya kuat dan kontennya viral.