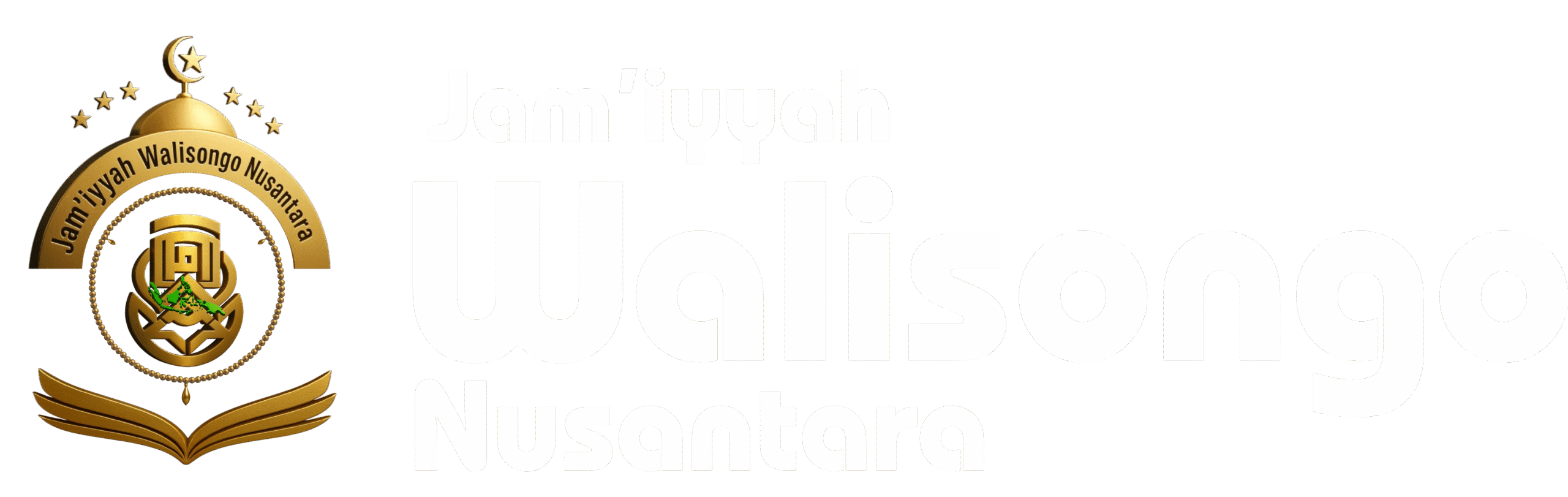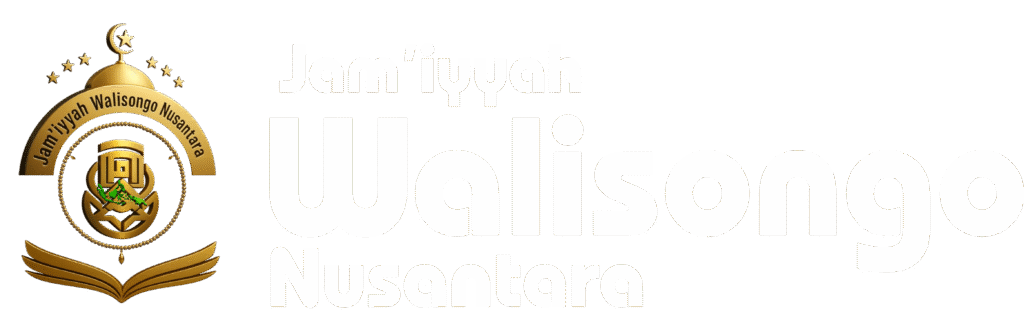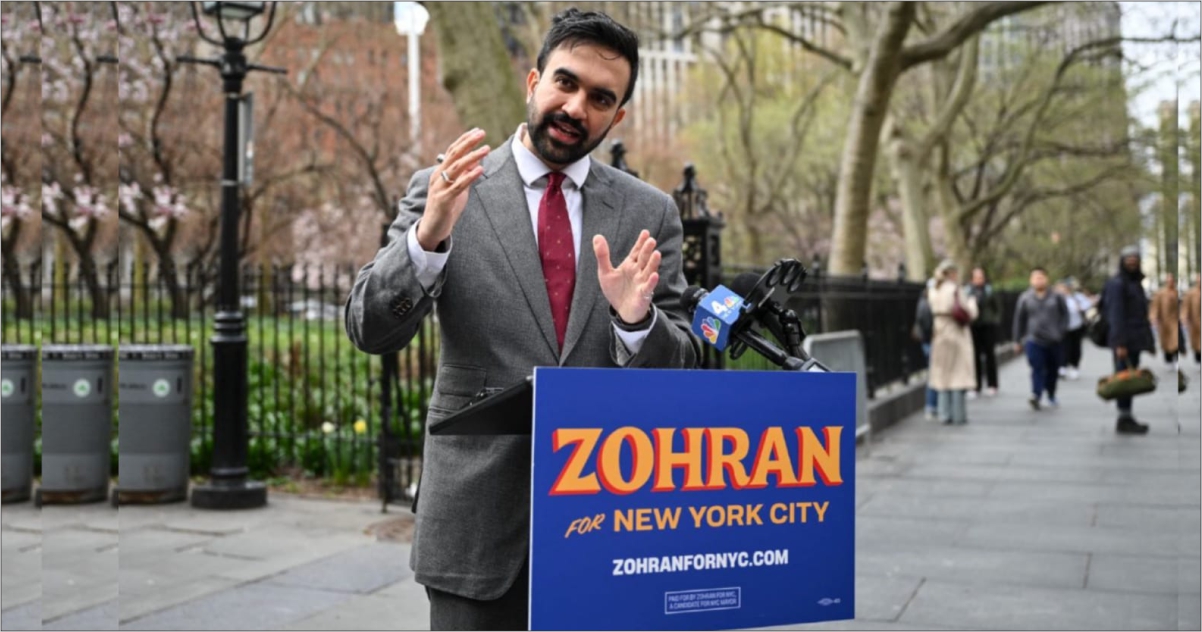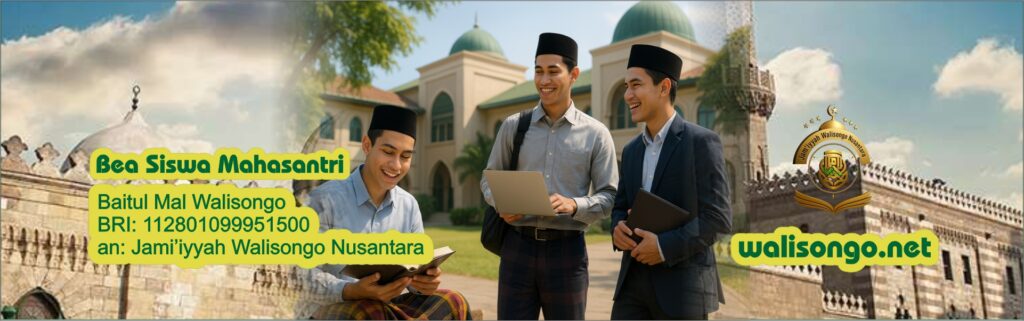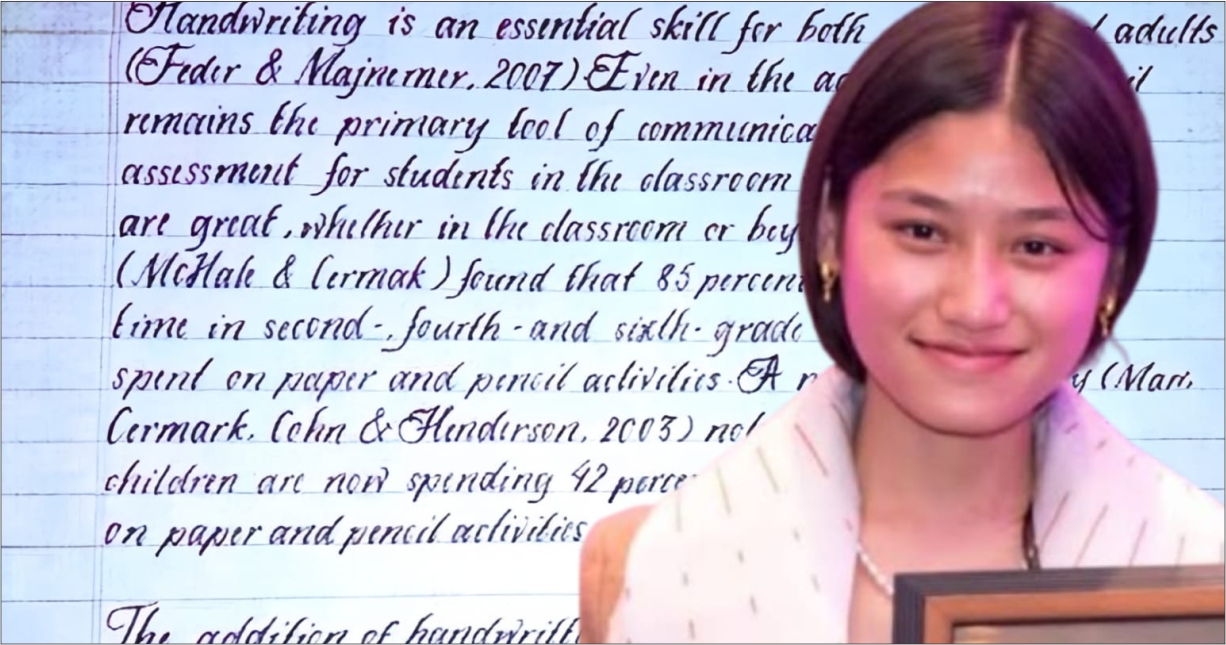Bendera setengah tiang berkibar di Anfield, tapi rasanya langit seluruh kota Liverpool pun turut mendung. Bukan karena kabut industrial klasik ala Inggris, tapi karena kabut duka yang menyelimuti hati jutaan pecinta sepak bola.
Diogo Jota, penyerang mungil tapi penuh daya dobrak, telah tiada. Ia bukan sekadar kehilangan untuk Liverpool —ia adalah kehilangan untuk kemanusiaan. Jota dan adiknya Andre Silva tewas dalam perjalanan menuju Inggris dari darat menyambung kapal feri.
Sepak bola memang sering disebut “the beautiful game”, tapi hari-hari ini ia terasa seperti drama klasik penuh tragedi, kehilangan, dan air mata. Bukan karena kalah 7-0 dari tim tetangga, tapi karena satu dari mereka yang mengenakan jersey merah itu takkan kembali lagi.
Ya, Jota pergi selamanya, dan tak mungkin kembali. Tidak untuk latihan, tidak untuk merayakan gol, dan tidak pula untuk menyeka air mata fans cilik di pinggir lapangan.
Ketika mendengar kabar duka ini, banyak dari kita berharap ini hanya salah satu hoaks yang biasa berseliweran di media sosial. Tapi ketika Presiden Portugal sendiri melayat, dan Virgil van Dijk memeluk istri Jota dengan mata sembab, kita tahu: ini nyata. Terlalu nyata.
Di satu nyanyian legendaris “You’ll Never Walk Alone,” ada satu janji: “When you walk through a storm, hold your head up high…” Kini, badai duka sedang menyapu keluarga Jota. Tapi mereka tidak berjalan sendiri. Ada Liverpool di belakang mereka. Bukan hanya klub, tapi institusi kasih sayang.
Di dunia sepak bola modern, pemain adalah aset. Kontrak ditulis dalam angka yang membuat ahli matematika bingung. Bonus dibayarkan per gol, per assist, bahkan per senyuman di sesi foto jersey baru.
Tapi ketika Diogo Jota mengembuskan napas terakhirnya, Liverpool tidak melihat angka. Mereka melihat keluarga. Dan mereka merespons bukan dengan kalkulator, tapi dengan hati.
Gaji 140.000 pound per pekan? Serahkan semuanya pada istrinya. Bonus yang belum sempat ditransfer? Masukkan ke dalam paket cinta. Dan itu berlaku untuk dua tahun sisa masa kontrak, berarti total sekitar Rp 325 miliar. Pendidikan ketiga anak Jota? Biar kami yang tanggung.
Bahkan, menurut bisik-bisik yang belum sepenuhnya dikonfirmasi, mereka akan tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga besar The Reds. Tak ada klausul “berakhir saat napas berhenti”. Karena bagi Liverpool, cinta tidak mengenal masa kontrak.
Banyak klub lain akan menyerahkan soal tersebut pada asuransi. Sistem sudah mengaturnya. Tapi Liverpool tak sekadar menjalankan sistem. Mereka membangun makna. This Means More, begitu semboyan mereka. Dan sekarang kita tahu, itu bukan hanya slogan iklan.
Jota bukan Messi. Ia bukan Ronaldo. Tapi ia adalah Jota. Seorang yang mencetak gol tak hanya di lapangan, tapi di hati para fans. Ia adalah pemain yang tidak banyak gaya, tapi banyak kerja. Tidak banyak drama, tapi banyak cinta.
Lihatlah caranya menyapa fans, memberi jersey untuk anak-anak kecil yang mengelu-elukan Liverpool di pinggir lapangan. Jota tak segan menolong rekan setim yang jatuh. Bahkan ketika tidak mencetak gol, ia mencetak simpati.
Sekarang, Anfield kehilangan bukan hanya seorang striker. Tapi juga seorang panutan. Seorang suami, ayah, teman, dan inspirasi. Seorang yang tetap menunduk saat dielu-elukan, dan tetap berlari kencang bahkan saat tertinggal.
Langkah Liverpool untuk hadir di pemakaman Jota bukan protokoler. Itu personal. Van Dijk tak perlu bicara, matanya cukup berkata-kata. Andy Robertson tak perlu mencetak umpan, kehadirannya di sisi keluarga Jota sudah cukup jadi pelipur lara.
Bahkan tampak hadir Arne Slot, pelatih baru yang belum sempat benar-benar mengenal Jota, berdiri di barisan paling depan. Ia menunjukkan bahwa di Liverpool, pelatih bukan bos, tapi bagian dari keluarga.
Mereka datang bukan sebagai pesepakbola. Tapi sebagai manusia. Mereka tidak membawa bola, tapi membawa pelukan. Tidak membawa strategi, tapi membawa simpati.

Diogo Jota telah pergi, tapi ia meninggalkan warisan. Bukan hanya statistik dan medali, tapi nilai. Bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal peduli. Soal loyalitas yang tetap hidup, bahkan ketika orangnya telah tiada.
Apa amal yang pernah dilakukan Jota semasa hidupnya? Barangkali ia tidak membuka panti asuhan atau membangun rumah ibadah. Tapi ia telah menunjukkan kebaikan dalam keseharian. Ia tersenyum. Ia memberi. Ia rendah hati. Dan ia tidak pernah menyombongkan diri walau dipuja ribuan orang. Itu cukup untuk menjadikannya teladan.
Terima kasih, Diogo Jota. Terima kasih, Liverpool. Dalam dunia yang semakin dingin dan legalistik, kalian mengingatkan kami bahwa cinta dan kemanusiaan masih punya tempat. Dan ya, Jota: You’ll Never Walk Alone. Bahkan dalam kepergianmu di usia 28 tahun.