Gelombang konten pendek yang masif di media sosial kini menimbulkan kekhawatiran serius di dunia pendidikan dan tumbuh kembang anak. Fenomena yang dikenal sebagai “brain rot” ini, sebuah perubahan mental akibat kebiasaan digital yang merusak, mulai mengikis kemampuan konsentrasi dan nalar generasi muda secara diam-diam. Anak-anak yang dulunya mudah terlibat dalam aktivitas belajar kini menunjukkan tanda-tanda cepat bosan dan sulit fokus, terbiasa dengan pola konsumsi konten digital yang serba instan.
Devinta Puspita Ratri, S.Pd., M.Pd, pakar linguistik dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya (UB), menyampaikan keprihatinannya. Ia menjelaskan bahwa “brain rot” bukanlah kerusakan otak secara fisik, melainkan pergeseran mental yang diakibatkan oleh kebiasaan digital yang tidak sehat.
“Konten-konten pendek membuat otak terbiasa bekerja dalam waktu singkat. Akibatnya, anak-anak menjadi tidak sabaran, sulit fokus, dan kehilangan minat untuk membaca,” jelas Devinta, menguraikan dampak nyata pada perilaku belajar.
Devinta juga menyoroti bagaimana tren ini tidak hanya memengaruhi proses belajar, tetapi juga cara anak-anak mengonsumsi dan memproduksi konten. Banyak dari mereka, katanya, lebih tertarik mengejar popularitas di media sosial daripada memikirkan isi dan nilai dari apa yang mereka unggah.
“Banyak dari mereka hanya mengejar popularitas di media sosial tanpa memperhatikan kualitas kontennya. Ini menumbuhkan budaya instan dan dangkal,” ujarnya, menggarisbawahi pergeseran prioritas di kalangan anak muda.
Dalam pandangannya, teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) pun turut berkontribusi terhadap kemunduran pola pikir jika tidak digunakan secara bijak. “Sekarang banyak yang hanya mengandalkan AI tanpa mau memahami, padahal berpikir kritis itu tetap harus dilatih,” tambahnya, menekankan pentingnya pengembangan kemampuan analitis.
Tak hanya berdampak pada kognisi, “brain rot” juga membawa konsekuensi sosial dan emosional yang mengkhawatirkan. Devinta memberikan contoh ekstrem, di mana pemahaman dasar anak-anak kini menurun drastis. Ia bahkan menemukan kasus anak yang mengira Garut adalah negara di Eropa.
“Beberapa komentar anak di media sosial menunjukkan rendahnya pemahaman dasar. Bahkan ada yang menyebut Garut sebagai negara di Eropa. Ini sangat mengkhawatirkan,” katanya, menggambarkan kesenjangan pengetahuan umum yang signifikan.
Menyikapi fenomena ini, Buya Munawwir Al-Qosimi, seorang ulama dan cendekiawan, turut menekankan pentingnya membudayakan kembali tradisi membaca dan menulis pada anak-anak, sekalipun dunia terus berubah seiring perkembangan digital. Menurutnya, nilai-nilai dasar dalam Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu dan mendokumentasikannya.
“Tradisi membaca dan menulis adalah akar peradaban Islam. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca,” ujar Buya Munawwir, merujuk pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Alaq ayat 1-5:
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ – اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ – الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ – عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”
Buya Munawwir menambahkan, ayat ini secara gamblang menunjukkan betapa pentingnya aktivitas membaca sebagai gerbang ilmu, dan pena (menulis) sebagai sarana untuk mengabadikan ilmu tersebut. “Meski teknologi berkembang pesat, esensi mencari ilmu dan mendokumentasikannya tidak boleh luntur,” tegasnya.
Ia juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang mendorong umatnya untuk mencatat ilmu. Salah satu riwayat menyebutkan:
“Ikatlah ilmu dengan menuliskannya.” (HR. Ad-Dailami)
“Hadis ini menjadi pengingat bahwa tulisan adalah pengikat ilmu. Tanpa menulis, ilmu bisa terbang dan terlupakan. Generasi muda kita harus dibiasakan menuangkan pemikiran mereka, mencatat pelajaran, dan membaca literatur yang mendalam, bukan hanya sebatas konten instan,” pungkas Buya Munawwir.

Menghadapi fenomena ini, Devinta menegaskan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak-anak menggunakan perangkat digital. Selain membatasi waktu layar, anak perlu dikenalkan pada kegiatan alternatif yang lebih produktif seperti membaca buku, bermain secara fisik, atau bersosialisasi langsung.
“Anak-anak harus dikenalkan pada digital hygiene, yaitu kemampuan memilah konten yang bermanfaat,” jelasnya, menekankan literasi digital yang esensial.
Sekolah juga punya tanggung jawab besar untuk mengembangkan cara berpikir kritis siswa, bukan hanya terpaku pada penyampaian materi akademik. Lebih lanjut, Devinta mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Kominfo, untuk lebih tegas menyaring konten-konten tidak mendidik yang tersebar luas di media sosial.
“Konten-konten receh dan sensasional masih banyak berseliweran. Ini tugas bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat,” tegas Devinta. Ia pun menutup pernyataannya dengan ajakan kepada semua pihak untuk saling bergandengan tangan dalam menghadapi tantangan digitalisasi yang makin kompleks.
“Fenomena brain rot ini hanya bisa dicegah dengan kerja kolektif. Semua harus ambil peran,” pungkasnya, menyerukan kolaborasi demi masa depan generasi penerus.

Jakarta (Walisongo.net) – Kementerian Agama Republik Indonesia sukses menggelar “Ngaji Budaya” dengan tema “Tradisi Muharram di Nusantara: Pesan Ekoteologi dalam Perspektif Kearifan Lokal” pada Senin (23/6/2025) di Auditorium HM Rasjidi, Jakarta. Acara ini merupakan bagian integral dari rangkaian kegiatan bertajuk “Peaceful Muharram” yang diselenggarakan Kemenag dalam menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Kehadiran acara ini menegaskan komitmen Kementerian Agama dalam menggali dan menyelaraskan nilai-nilai keislaman dengan kearifan lokal serta isu-isu kontemporer.
Giat ini tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga mempertemukan berbagai kalangan. Acara ini menghadirkan budayawan dan pemikir kebangsaan terkemuka, Kiyai Sastro Al Ngatawi, sebagai narasumber utama. Selain itu, kegiatan ini dihadiri oleh para penghulu dari berbagai daerah, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama, serta disiarkan secara langsung melalui berbagai platform media sosial resmi Kemenag, memastikan pesan-pesan penting dapat menjangkau khalayak yang lebih luas.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam sambutannya menegaskan bahwa peringatan 1 Muharram bukan sekadar rutinitas tradisi belaka. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa momen ini adalah kesempatan emas untuk kontemplasi dan pensucian diri, baik secara lahiriah maupun batiniah. “Memperingati 1 Muharram ini bukan melestarikan bid’ah. Justru kalau paham konsep ekoteologi, sulit untuk musyrik,” ungkap Menag, menjelaskan bahwa pemahaman mendalam tentang hubungan manusia dengan alam justru akan menjauhkan dari syirik.
Beliau melanjutkan bahwa pesan ekoteologi sejatinya sangat selaras dengan esensi 1 Muharram. Bulan Muharram, sebagai salah satu bulan haram dalam Islam, secara historis melarang peperangan dan konflik. Oleh karena itu, momentum ini sangat tepat untuk melakukan introspeksi diri dan memperbarui komitmen kedamaian. Menurut Menag, tradisi peringatan 1 Muharram juga merupakan bentuk apresiasi mendalam terhadap waktu. Ia menyoroti bagaimana setiap waktu dan tempat memiliki kesakralan serta nilai tersendiri dalam perspektif Islam, seperti halnya salat di depan Ka’bah yang bernilai seratus ribu kali lipat dibandingkan tempat lain.
“Momen peringatan 1 Muharram ini adalah sarana penajaman hati nurani,” tegas Menag Nasaruddin. Ia mengajak seluruh hadirin untuk merenungi kedalaman batin, bahkan dengan gestur simbolis seperti duduk di lantai tanpa kursi. Menurutnya, hal ini berfungsi sebagai “kekuatan simbolik” dan “shock therapy” untuk membangkitkan kesadaran jiwa yang mungkin telah tumpul oleh kesibukan duniawi.

Menag juga menekankan bahwa penghormatan terhadap waktu dan tempat suci sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan adalah universal, ditemukan dalam berbagai agama dan budaya. Melalui konsep ekoteologi, manusia diajak untuk menyadari bahwa diri adalah bagian tak terpisahkan dari alam semesta. Hubungan ini bersifat resiprokal; ketika manusia menjaga alam, alam pun akan menjaga manusia.
“Orang yang menyatu dengan alam tidak hanya mencintai bunga yang mekar, tapi juga bunga yang layu dan gugur. Karena dalam pandangan ekoteologi, semua fase kehidupan memiliki makna dan layak dicintai,” jelasnya. Pesan ini mendorong perspektif holistik terhadap kehidupan, di mana setiap ciptaan memiliki nilai dan patut dihormati. Menag mengajak umat untuk menumbuhkan semangat ekoteologis, yakni mencintai ciptaan sebagai bagian dari diri sendiri, dan memperlakukan alam dengan kasih dan hormat, sebagai manifestasi nyata dari keimanan.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam), Abu Rokhmad, menambahkan bahwa Ngaji Budaya ini merupakan kelanjutan dari rangkaian “Peaceful Muharram”, setelah sebelumnya Kementerian Agama sukses menggelar kegiatan Car Free Day (CFD) pada 22 Juni 2025 yang melibatkan ribuan peserta.
Dalam laporannya, Abu Rokhmad menyampaikan bahwa Ngaji Budaya ini mengangkat dua pesan utama yang diharapkan mampu tersampaikan secara luas kepada masyarakat Indonesia: tradisi Muharram di Nusantara dan pentingnya kesadaran ekoteologis. “Di berbagai daerah, masyarakat memperingati Muharram dengan ragam tradisi. Di Jawa misalnya, dikenal tradisi 1 Suro. Di Semarang, masyarakat mandi di sungai atau ‘adus kungkum’ sebagai bentuk permohonan energi dan semangat baru,” paparnya, menyoroti kekayaan budaya lokal yang lekat dengan peringatan hari besar Islam. Ia menekankan perlunya menggali kembali dan menyinergikan tradisi-tradisi ini dengan nilai-nilai keagamaan.
Lebih lanjut, Abu Rokhmad juga menyoroti relevansi pesan ekoteologi dalam kearifan lokal. Ia memberikan contoh bagaimana orang tua zaman dahulu sering “menakut-nakuti” anak-anak agar tidak mandi di danau karena ada “buaya putih”. “Tapi sejatinya, itu adalah cara menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah eksploitasi alam,” pungkasnya. Hal ini menunjukkan bagaimana leluhur telah mewariskan cara-cara bijak untuk menjaga lingkungan melalui narasi dan tradisi lisan, yang kini dapat dimaknai ulang dalam konteks ekoteologi modern.
Kegiatan Ngaji Budaya ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang makna spiritual Tahun Baru Islam, sekaligus mendorong kesadaran kolektif untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan sebagai wujud ibadah dan pelestarian warisan budaya bangsa.
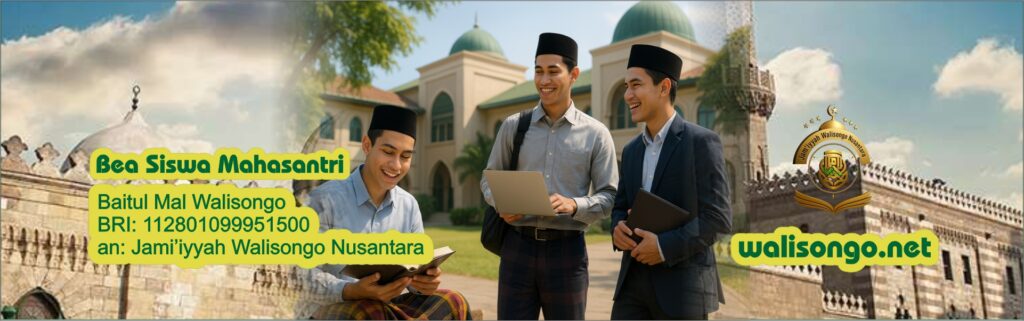
Kerajaan Majapahit, di bawah tampuk kepemimpinan Raja Hayam Wuruk (memerintah 1350-1389 M), seringkali diidentikkan dengan puncak kejayaan peradaban Hindu-Buddha di Nusantara. Karya-karya monumental seperti Negarakertagama yang mengisahkan kemaharajaan besar dengan wilayah pengaruh luas, seolah mengukuhkan citra tersebut. Namun, di tengah kemilau Hindu-Buddha itu, sebuah narasi penting lain mulai terkuak: benih-benih agama Islam ternyata telah mulai tumbuh dan menyebar, bahkan di jantung pusat pemerintahan kerajaan.
Penemuan dua situs bersejarah, Makam Tralaya dan Makam Puteri Campa, menjadi bukti konkret yang tak terbantahkan mengenai kehadiran dan perkembangan Islam di wilayah yang kini dikenal sebagai Jawa Timur, jauh sebelum era Walisongo yang lebih dikenal luas dalam historiografi Islam di Jawa. Temuan ini menantang pandangan tradisional dan memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas Majapahit.
Kompleks Makam Tralaya, yang berlokasi strategis di area yang diyakini sebagai bekas ibu kota Majapahit (sekarang Trowulan, Mojokerto), telah menjadi magnet bagi para sejarawan dan arkeolog sejak lama. Sejumlah peneliti terkemuka dari masa kolonial hingga modern, seperti PJ Veth, Verbeek, Knebel, Krom, dan L Ch Damais, telah menaruh perhatian besar pada situs ini, mencoba mengurai misteri di balik batu-batu nisannya.
PJ Veth, seorang orientalis dan ahli geografi Belanda, adalah salah satu yang pertama kali mengungkapkan keberadaan data Islam di Makam Tralaya. Dalam analisisnya, ia mencatat adanya inskripsi pada batu nisan di Makam Tralaya yang ditulis dengan kombinasi huruf Jawa kuno dan Arab. Ini adalah temuan krusial, mengingat mayoritas artefak sezaman di Majapahit didominasi oleh aksara dan simbol Hindu-Buddha.

Lebih lanjut, Sjamsudduha dalam karyanya yang monumental, “Corak dan Gerak Hinduisme dan Islam di Jawa Timur,” menguraikan detail inskripsi tersebut. Ia menjelaskan bahwa meskipun angka tahun pada nisan-nisan umumnya tercatat dalam huruf Jawa kuno dan tahun Saka, di balik beberapa nisan itu terdapat tulisan Arab yang sangat penting: kalimat tayyibah (seperti “La ilaha illallah” atau “Bismillah”). Kehadiran kalimat-kalimat sakral dalam Islam ini secara definitif menunjukkan bahwa mereka yang dimakamkan di sana adalah pemeluk agama Islam.
Verbeek, dalam laporannya, pernah menyebutkan adanya lima nisan yang jelas bertuliskan Arab, meskipun beberapa di antaranya kini telah hilang akibat faktor alam dan tangan manusia. Namun, dari nisan-nisan yang masih bertahan di kompleks Makam Tralaya, beberapa tercatat bertarikh tahun 1397 Saka dan 1399 Saka. Jika dikonversi ke Masehi, dengan perhitungan kasar (tahun Saka + 78 tahun), ini menunjukkan sekitar tahun 1475-1477 Masehi. Namun, penting untuk dicatat bahwa penelitian lebih lanjut dan pembacaan angka tahun yang tergores pada nisan-nisan di Tralaya menyimpulkan rentang waktu yang lebih luas, yaitu dari tahun 1298 Saka hingga 1533 Saka (sekitar 1376 Masehi hingga 1611 Masehi).
Rentang waktu yang luas ini sangat signifikan. Awalnya, yaitu sekitar 1376 Masehi, berada dalam periode aktif pemerintahan Raja Hayam Wuruk (1350-1389 M). Hal ini secara tegas mengindikasikan bahwa di ibu kota Kerajaan Majapahit atau di wilayah sekitarnya, pada masa keemasan Hayam Wuruk, sudah ada komunitas pemeluk agama Islam. Peneliti terkemuka seperti M.C. Ricklefs bahkan berpendapat bahwa pemeluk-pemeluk Islam awal ini adalah orang-orang Jawa asli, menepis anggapan bahwa Islam hanya dibawa oleh pedagang asing.
Selain Makam Tralaya, sebuah temuan nisan lain yang tak kalah strategis berada di Makam Puteri Campa, yang terletak di sebelah tenggara Museum Trowulan, Mojokerto. Nisan ini menampilkan kombinasi unik dari inskripsi angka tahun dengan huruf Kawi (Jawa kuno) dan Arab, serta dilengkapi dengan gambar yang kuat diduga merupakan lambang Kerajaan Majapahit.
Identitas “Puteri Campa” itu sendiri telah menjadi topik perdebatan hangat di kalangan sejarawan. Beberapa narasi tradisional dan babad Jawa mengaitkannya dengan seorang bibi dari Sunan Ampel, salah satu Walisongo terkemuka, yang kemudian dipercaya menjadi istri Raja Majapahit.
HJ De Graaf, seorang sejarawan Belanda yang banyak meneliti sejarah Jawa, sebagaimana dijelaskan kembali oleh Sjamsudduha dalam bukunya, menyatakan bahwa Puteri Campa ini adalah istri raja Majapahit yang terakhir. Sementara itu, ada pendapat lain yang lebih spesifik yang menyebutkan Puteri Campa merupakan istri dari Raja Majapahit Bhre Tumapel, yang berkuasa antara 1447-1451 Masehi.
Terlepas dari perbedaan penafsiran mengenai raja Majapahit mana yang ia nikahi, keberadaan nisan Puteri Campa dengan inskripsi Islam dan lambang kerajaan adalah bukti yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa ia adalah istri raja, atau setidaknya seorang tokoh yang sangat berpengaruh dan termasuk dalam lingkaran dalam sistem keprabuan (kerajaan) Majapahit. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menyebar di kalangan rakyat biasa atau pedagang, tetapi juga telah menembus strata sosial tertinggi dan mungkin saja memengaruhi dinamika internal istana.
Penemuan-penemuan di Makam Tralaya dan Makam Puteri Campa memberikan perspektif yang lebih kaya dan bernuansa tentang sejarah Majapahit dan proses islamisasi di Nusantara. Kisah Majapahit tidak lagi sekadar tentang kejayaan Hindu-Buddha yang kemudian runtuh, tetapi juga tentang sebuah entitas kompleks yang secara perlahan namun pasti telah berinteraksi dan mengasimilasi elemen-elemen Islam dalam masyarakatnya.
Nisan-nisan ini menjadi bukti nyata bahwa proses islamisasi di Jawa dan Nusantara bukanlah peristiwa instan atau melalui penaklukan militer semata, melainkan sebuah proses panjang yang bertahap, damai, dan mungkin terjadi melalui jalur perdagangan, pernikahan, serta akulturasi budaya. Kehadiran komunitas Muslim di pusat kekuasaan Majapahit menunjukkan adanya toleransi beragama dan koeksistensi yang harmonis, setidaknya pada periode-periode awal.
Jejak-jejak ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa sejarah adalah mosaik yang terus diperkaya dengan temuan-temuan baru. Dengan terus menggali dan menafsirkan ulang bukti-bukti arkeologis, kita dapat memahami masa lalu dengan lebih komprehensif, menghilangkan mitos, dan memberikan apresiasi yang lebih mendalam terhadap kompleksitas perjalanan peradaban Nusantara.

Sumber-Sumber Referensi:
Berikut adalah surat Ir. Soekarno kepada T. A. Hassan yang ditulis dari Ende pada 1 Desember 1934:
SURAT-SURAT ISLAM DARI ENDEH
No. 1. Endeh, 1 Desember 1934
Assalamu’alaikum,
Jikalau saudara-saudara memperkenankan, saya minta saudara mengasih hadiah kepada saya buku-buku yang tersebut di bawah ini:
Kemudian daripada itu, jika saudara-saudara ada sedia, saya minta sebuah risalah yang membicarakan soal “sayid”. Ini buat saya bandingkan dengan alasan-alasan saya sendiri tentang hal ini. Walaupun Islam zaman sekarang menghadapi soal-soal yang beribu-ribu kali lebih benar dan lebih sulit daripada soal “sayid” itu, maka toh menurut keyakinan saya, salah satu kecelaan Islam zaman sekarang ini, ialah pengeramatan manusia yang menghampiri kemusyrikan itu. Alasan-alasan kaum “sayid”, misalnya mereka punya brosur “Bukti Kebenaran”, saya sudah baca, tetapi tak bisa meyakinkan saya. Tersesatlah orang yang mengira, bahwa Islam mengenal suatu “aristokrasi Islam”. Tiada satu agama yang menghendaki kesama-rataan lebih daripada Islam. Pengeramatan manusia itu, adalah salah satu sebab yang mematahkan jiwanya sesuatu agama dan umat, oleh karena pengeramatan manusia itu, melanggar tauhid. Kalau tauhid rapuh, datanglah kebencanaan!
Sebelum dan sesudahnya terima itu buku-buku, yang saya tunggu-tunggu benar, saya mengucap beribu-ribu terima kasih.
Wassalam,
SUKARNO

Surat Ir. Soekarno dari Ende , Flores, NTT ini bukan sekadar permintaan buku, melainkan sebuah pernyataan sikap dan pemikiran mendalam tentang prinsip-prinsip fundamental Islam. Soekarno menunjukkan minatnya yang besar terhadap literatur keagamaan, mencerminkan dahaganya akan ilmu dan pemahaman Islam yang komprehensif. Daftar buku yang diminta—mulai dari “Pengajaran Shalat” hingga “Utusan Wahabi”—mengindikasikan bahwa ia ingin mendalami fikih, akidah, dan isu-isu kontemporer yang relevan pada masanya.
Namun, bagian paling krusial dari surat ini adalah kritiknya terhadap fenomena “sayid” dan pengeramatan manusia. Soekarno dengan tegas menyatakan bahwa praktik semacam itu menghampiri kemusyrikan dan menjadi salah satu “kecelaan Islam zaman sekarang.” Ia telah membaca argumen dari kaum “sayid” namun tidak merasa yakin. Gelar sayyid saat itu dipakai oleh keluarga Ba’alawi, yang sekarang dikenal dengan sebutan “Habib”
Poin utama Soekarno adalah bahwa Islam tidak mengenal “aristokrasi Islam”. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa “tiada satu agama yang menghendaki kesama-rataan lebih daripada Islam.” Baginya, pengeramatan manusia adalah pelanggaran terhadap tauhid, dan jika tauhid rapuh, “datanglah kebencanaan!” Ini adalah peringatan keras dari Soekarno tentang bahaya penyimpangan akidah.
Kritik Soekarno ini sangat relevan dengan konteks saat itu, dan bahkan hingga kini, ketika ada kelompok-kelompok tertentu, seperti keluarga Ba’alawi, yang cenderung membanggakan dan mengutamakan nasab mereka yang diklaim sebagai keturunan Rasulullah SAW. Soekarno melihat penekanan berlebihan pada nasab sebagai bentuk pengeramatan yang bertentangan dengan esensi ajaran Islam tentang kesetaraan dan keesaan Allah.
Pandangan Soekarno didukung kuat oleh ajaran dasar Al-Qur’an dan Hadits yang menekankan kesetaraan manusia di hadapan Allah dan melarang pembanggakan nasab.
1. Kesetaraan Berdasarkan Takwa
Islam mengajarkan bahwa satu-satunya tolok ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan garis keturunannya.
Al-Qur’an, Surat Al-Hujurat Ayat 13:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”
Ayat ini adalah fondasi utama bagi prinsip kesetaraan dalam Islam, menegaskan bahwa asal-usul genetik tidak menentukan kedudukan spiritual.
2. Larangan Membanggakan Nasab
Rasulullah SAW sendiri secara eksplisit melarang umatnya untuk membanggakan nasab, mengingatkan bahwa semua manusia memiliki asal yang sama.
Hadits dari Abu Hurairah: Rasulullah SAW bersabda:
لَا تَفَاخَرُوا بِأَنْسَابِكُمْ فَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ
“Janganlah kalian saling membanggakan nasab kalian, sesungguhnya semua manusia itu berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah.” (HR. Ahmad)
Hadits ini menekankan kesederhanaan asal-usul manusia dan meniadakan alasan untuk merasa superior berdasarkan garis keturunan.
3. Amal Lebih Utama dari Nasab
Bahkan bagi kerabat terdekat Rasulullah SAW, beliau menegaskan bahwa amal perbuatanlah yang akan menjadi penentu keselamatan di akhirat, bukan nasab.
Hadits dari Abu Hurairah: Ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW bersabda:
يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
“Wahai sekalian orang Quraisy, belilah diri kalian dari Allah (dengan beramal saleh), sungguh aku tidak dapat menolong kalian sedikitpun dari (siksaan) Allah.” (HR. Muslim)
Dan kepada putri beliau sendiri:
يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اعْمَلِي فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
“Wahai Fatimah putri Muhammad, beramallah (saleh), karena sungguh aku tidak dapat menolongmu sedikitpun dari (siksaan) Allah.” (HR. Muslim)
Ini adalah penegasan kuat bahwa tanggung jawab individu atas amalnya adalah mutlak, dan nasab tidak dapat menjadi jaminan penyelamat.

Pesan Sunan Ampel: “Ojo Gumunggung Karo Nasab”
Pesan Sunan Ampel: “Ojo gumunggung karo nasab, sebab dadi sirnane barokah” (Janganlah membanggakan nasab, karena akan menghilangkan keberkahan) sangat selaras dengan kritik Soekarno dan ajaran Islam yang universal.
Pernyataan ini mencerminkan kearifan lokal yang menguatkan prinsip-prinsip syariat:
Hilangnya keberkahan (“sirnane barokah”) dapat diartikan sebagai berkurangnya manfaat dan kebaikan dalam hidup, baik secara spiritual maupun sosial, karena seseorang telah menyimpang dari tujuan utama penciptaan dan prinsip-prinsip agama yang luhur.

Perbedaan Pendekatan dengan Keluarga Wali Songo dan Ir. Soekarno
Perdebatan mengenai nasab Ba’alawi ini sangat kontras dengan sikap yang ditunjukkan oleh keluarga Wali Songo dan juga Ir. Soekarno sendiri.
Perbedaan mendasar terletak pada:
Sikap terhadap Pengakuan Publik: Keluarga Wali Songo tidak memaksakan apalagi menuntut orang lain untuk mempercayai nasab mereka. Mereka membiarkan bukti amal dan pengaruh baik yang berbicara. Sebaliknya, sebagian pihak yang membanggakan nasab Ba’alawi cenderung menuntut pengakuan dan terkadang bahkan mengklaim keistimewaan yang berlebihan.
Tujuan Penekanan Nasab: Bagi sebagian Ba’alawi, nasab ditekankan untuk menunjukkan status kemuliaan dan keistimewaan, bahkan terkadang untuk menuntut penghormatan khusus. Bagi keluarga Wali Songo dan Soekarno, nasab (jika ada) adalah bagian dari sejarah pribadi dan keluarga, tetapi bukan untuk dibanggakan atau dijadikan alat legitimasi kekuasaan spiritual/sosial.
Fokus Dakwah: keluarga Wali Songo dan Soekarno fokus pada pengajaran Islam yang substantif (tauhid, syariah, akhlak), persatuan umat, dan pembangunan masyarakat. Sedangkan penekanan berlebihan pada nasab dapat mengalihkan fokus dari esensi ajaran Islam.
Baca juga:https://id.m.wikisource.org/wiki/Surat-Surat_Islam_dari_Ende
Walisongo.net dengan bangga mempersembahkan ulasan mendalam mengenai salah satu permata intelektual dari Tanah Air, Syekh Junaid al-Batawi. Seringkali, masyarakat Betawi identik dengan humor dan ceplas-ceplos, yang terkadang menutupi kedalaman intelektual yang mereka miliki. Padahal, sejak abad ke-18, kiprah intelektual Betawi sudah diakui bahkan di Tanah Suci dan memiliki peran besar dalam membangun fondasi keislaman di Indonesia. Salah satu poros utamanya adalah Syekh Junaid al-Batawi, ulama kelahiran Pekojan, Jakarta Barat, yang jaringannya meluas ke seluruh penjuru dunia Islam pada awal abad ke-19. Kisah beliau bukan hanya tentang keilmuan, tetapi juga tentang sebuah warisan silsilah yang menghubungkannya langsung dengan para pendiri peradaban Islam di Nusantara.
Syekh Junaid al-Batawi tidak hanya dikenal karena keilmuannya yang mendalam, tetapi juga karena silsilah keturunannya yang luar biasa, menunjukkan garis darah biru yang mengalir dalam dirinya. Silsilah ini menghubungkannya dengan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam di Jawa, termasuk para pendiri Kesultanan Demak dan bahkan salah satu Wali Songo.
Berikut adalah runtutan silsilah beliau yang berhasil didokumentasikan, menampilkan mata rantai kebangsawanan dan keilmuan:
Yang paling menarik dari silsilah ini adalah pernikahan Raden Fattah dengan Dewi Murtashimah / Asyikah / Ratu Panggung binti Makhdum Sunan Ampel Al Bukhari Al Kazhimi Al Husaini. Ini menandakan adanya korelasi erat antara garis keturunan Raden Fattah dengan Sunan Ampel, salah satu Wali Songo yang sangat krusial dalam penyebaran Islam di Jawa. Dengan demikian, Syekh Junaid al-Batawi memiliki ikatan darah langsung sebagai cucu dari Sunan Ampel, memperkuat posisinya sebagai figur sentral dalam jaringan keilmuan Islam Nusantara.
Selain silsilah di atas, Raden Fattah Demak juga diketahui memiliki garis keturunan dari pihak lain, yang semakin memperkaya akar keilmuan dan keagamaan beliau:
Silsilah ini semakin memperkuat pemahaman kita tentang betapa dalamnya akar keilmuan dan keagamaan dari Raden Fattah, yang merupakan cikal bakal Kesultanan Demak. Nama Syekh Abdullah Darqom atau Syekh Bentong serta Syekh Hasanudin Quro Al Jailani Al Hasani menunjukkan adanya hubungan dengan para ulama besar yang memiliki sanad keilmuan yang kuat. Ini menegaskan bahwa Syekh Junaid al-Batawi lahir dari lingkungan yang kental dengan tradisi keilmuan Islam dan memiliki silsilah yang terhubung dengan ulama-ulama besar di Nusantara maupun di Timur Tengah.
Data otobiografi Syekh Junaid al-Batawi memang tidak banyak terdokumentasi di tanah air. Namun, keberadaan dan pengaruh keilmuan beliau justru terkuak secara signifikan dalam catatan perjalanan orientalis terkemuka asal Belanda, C. Snouck Hurgronje (1936 M). Setelah berhasil menyusup ke Makkah pada 21 Januari 1885 dan tinggal selama tujuh bulan, Hurgronje menulis dalam jurnalnya, Mecca In The Latter Part Of 19th Century, bahwa di Makkah pada perempat ketiga abad ke-19, ada “sesepuh” (Nestor) para ulama Jawa yang berasal dari Tanah Betawi bernama “Junaid” yang sudah menetap selama 50 tahun. Diperkirakan, beliau sudah bermukim di Makkah sejak tahun 1834, tanpa diketahui pasti kapan waktu hijrahnya. Jika data ini akurat, berarti Syekh Junaid berhijrah ke Makkah dalam usia yang cukup matang, sekitar 30 tahun, membawa serta kekayaan intelektual dan spiritual dari Nusantara.
Sebagai seorang Imam Masjidil Haram, posisi Syekh Junaid al-Batawi sangatlah prestisius dan menunjukkan pengakuan atas keilmuan serta integritasnya. Rakhmad Zailani Kiki dkk dalam Genealogi Intelektual Ulama Betawi (2018), menyebutkan bahwa Syekh Junaid Al-Batawi adalah sosok yang sangat berpengaruh di Makkah. Beliau terkenal di seantero dunia Islam Sunni dan mazhab Syafi’i sepanjang abad ke-18 dan 19. Ini bukan hanya pencapaian pribadi, tetapi juga mengharumkan nama Indonesia di kancah global.
Ridwan Saidi mengungkapkan, Syekh Junaid al-Batawi memiliki banyak murid yang kemudian menjadi ulama terkemuka di tanah air bahkan dunia Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, pengarang Tafsir Al-Munir dan 37 kitab karangan lainnya yang masih diajarkan di berbagai pesantren Indonesia dan di luar negeri. Murid Syekh Junaid lainnya adalah Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif al-Minangkabawi, seorang imam, khatib, dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi’i. Berkat keluasan ilmunya, beliau diberi gelar “Syekh al-Masyāyikh” atau “Gurunya para guru”, sebuah gelar kehormatan yang menunjukkan posisi sentral Syekh Junaid dalam lingkaran keilmuan Islam. Murid Syekh Junaid lainnya adalah KH. Abdul Karim Tebuwung Dukun Gresik, yang dikenal sebagai “Guru Ulama Pantura” atau “Sunan Drajat Tebuwung.”
Kiprah dan pengaruh Syekh Junaid al-Batawi begitu besar hingga saat Makkah ditaklukkan pada tahun 1925 M dan diadakan perjanjian gencatan senjata antara Raja Ali bin Husein dengan Raja Ibnu Saud, keluarga Syekh Junaid masuk dalam daftar resmi pemerintah kerajaan yang diberi hak istimewa. Hal ini karena mereka telah menjalin hubungan baik dengan penguasa Makkah sebelumnya. Keturunan keluarga Betawi ini terdeteksi sejak 1987 M sampai sekarang dan masih tetap dalam perlindungan Kerajaan Saudi Arabia.
Ini adalah bukti konkret betapa besar kehormatan yang diberikan kepada Syekh Junaid dan keturunannya. Bahkan, konon keluarga besar Syekh Junaid yang bermukim di Jeddah biasa mengadakan acara Maulid dan Isra Miraj, meskipun kegiatan-kegiatan sejenis sangat “tabu” dilakukan kalangan ulama dan penguasa Arab Saudi karena perbedaan ideologi. Ini menunjukkan betapa terhormatnya nama Syekh Junaid al-Betawi di kalangan keluarga kerajaan, bahkan hingga saat ini, menunjukkan pengaruh spiritual dan sosialnya yang melampaui batas-batas politik dan mazhab.
Saking dihormatinya Syekh Junaid di Makkah, Buya Hamka (dalam Shahab, 2009) menulis, ketika Syarif Ali (putra Syarif Husin) ditaklukkan oleh Ibnu Saud, salah satu syarat penyerahannya adalah meminta “keluarga Syekh Junaid tetap dihormati setingkat dengan keluarga Raja Ibnu Saud.” Persyaratan ini diterima oleh Ibnu Saud, sebuah pengakuan yang tak ternilai harganya atas kontribusi dan kedudukan Syekh Junaid dalam sejarah Islam.
Sama halnya dengan tahun kelahirannya, tahun meninggalnya Syekh Junaid juga tak diketahui pasti. Menurut Direktur Islam Nusantara Center (INC), A Ginanjar Sya’ban, beliau meninggal pada akhir abad ke-19 Masehi. Adapun makam Syekh Junaid, kata Dosen Filologi dari Universitas Padjajaran itu, berada di kompleks Pemakaman Al-Ma’la, tak jauh dari Masjidil Haram, tempat pemakaman para tokoh besar Islam.
Alwi Shahab, budayawan Betawi, menulis tahun 1840 M sebagai tahun wafat Syekh Junaid di usianya yang ke 100 tahun di Tanah Suci. Namun, Ridwan Saidi meragukan analisis ini, karena pada tahun 1894-1895, ketika Snouck Hurgronje berhasil menyusup ke Makkah, Syekh Junaid diketahui masih hidup dalam usia yang sangat lanjut. Perbedaan data ini tidak mengurangi keagungan Syekh Junaid, justru menambah misteri dan kekaguman akan usianya yang panjang dan produktif.
Terlepas dari semua fakta ini, Syekh Junaid merupakan sosok teladan hebat yang mengabdikan sebagian besar usianya demi perkembangan khazanah Islam. Berkat kiprahnya yang sangat harum di dunia Islam internasional, nama Betawi pun turut harum. Syekh Junaid al-Batawi menjadi sosok yang sangat dihormati dan kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Barat, menggantikan nama Jalan Lingkar Luar Barat di Rawa Buaya, Cengkareng.
Kisah Syekh Junaid al-Batawi adalah pengingat yang kuat bahwa kekayaan intelektual dan spiritual masyarakat Betawi jauh melampaui stereotip yang ada. Beliau adalah bukti nyata bahwa Indonesia, khususnya Betawi, telah melahirkan ulama-ulama besar yang berperan penting dalam peta keilmuan Islam dunia. Semoga kisah inspiratif ini dapat memotivasi kita untuk terus menggali dan menghargai warisan intelektual para leluhur. [wallahu a’lam bish showab]
GRESIK – Ribuan jamaah dari berbagai penjuru Jawa Timur dan sekitarnya memadati Pondok Pesantren Al-Karimi, Tebuwung, Dukun, Gresik, hari ini, Rabu (11/6/2025), dalam rangka memperingati Haul ke-133 KH. Abdul Karim Tebuwung. Acara tahunan ini tak hanya mengenang sosok ulama kharismatik berjuluk “Sunan Drajat Tebuwung,” tetapi juga secara khusus menyoroti harmonisasi dan sinergi perjuangan beliau bersama sang istri, Nyai Mas Amirah binti Raden Jamilun, yang merupakan cucu Bupati Sidayu, serta keturunan Sunan Drajat dan Sayyid Qinan, dalam menghadapi tantangan dakwah dan penindasan kolonial, serta jejak rekam keturunan beliau dalam mengemban estafet dakwah melalui pesantren.
Acara haul diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an dan dilanjutkan dengan tahlil serta doa bersama yang dipimpin oleh para kyai dan habaib. Suasana khidmat terasa kental, diiringi lantunan shalawat yang mengajak jamaah merenungi perjalanan hidup dan dakwah kedua tokoh sentral ini.
Dalam kesempatan dan tempat yang lain , Ketua Umum Jam’iyyah Walisongo Nusantara (JAWARA), KH. Munawwir Al-Qosimi, yang banyak mengisahkan cerita ini, secara gamblang memaparkan tentang sosok KH. Abdul Karim Tebuwung. Beliau lahir di Drajat, Lamongan, pada 11 Syawal 1245 H (5 April 1830), dan merupakan keturunan langsung dari Sunan Drajat. KH. Abdul Karim mengabdikan hidupnya untuk menuntut ilmu hingga ke Tanah Suci Makkah, di mana beliau berguru kepada ulama-ulama besar seperti Syekh Ahmad Khatib asy-Syambasi, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dan Syekh Nawawi al-Bantani. Sanad inti keilmuan beliau adalah dari Sunan Drajat dan Sunan Ampel dan lainnya sanad sekunder.
KH. Munawwir Al-Qosimi lantas menekankan bahwa perjuangan dakwah KH. Abdul Karim tidak bisa dilepaskan dari peran vital Nyai Mas Amirah binti Raden Jamilun. “Beliau adalah sosok di balik kesuksesan dakwah Kiai Abdul Karim. Keduanya adalah pasangan yang saling melengkapi, saling mendukung dalam suka dan duka,” ungkap KH. Munawwir.
Nyai Mas Amirah memiliki latar belakang yang istimewa. Beliau adalah putri dari Raden Jamilun. Raden Jamilun sendiri merupakan putra dari Kanjeng Sepuh Sidayu (Raden Adipati Suryo Diningrat/Suryo Adiningrat) yang menikah dengan Dewi Wardah. Dewi Wardah ini adalah putri dari Sayyid Qinan. Dengan demikian, Nyai Mas Amirah merupakan cucu seorang Bupati Sidayu, memiliki trah kebangsawanan Mangkunegaran Solo, serta keturunan dari Sunan Drajat (melalui jalur Sayyid Qinan). Latar belakang kebangsawanan dan keilmuan yang kuat ini menunjukkan betapa besar pengorbanan beliau meninggalkan kenyamanan hidup demi berjuang bersama sang suami.
Salah satu babak kelam namun heroik dalam perjalanan hidup mereka sebelum pindah ke Tebuwung dan mendirikan pesantren adalah ketika pemerintah kolonial Belanda berniat mengangkat KH. Abdul Karim sebagai mufti Surabaya atau qodhi di kadipaten Sidayu. Beliau menolak tawaran tersebut dengan tegas, yang sontak memicu kemarahan Belanda. Sebagai bentuk tekanan, Belanda menyandera salah satu putri beliau di Sidoresmo, Surabaya.
Tak gentar, KH. Abdul Karim yang dikenal dengan keilmuan dan karomahnya, bersama keluarganya, menunjukkan perlawanan sengit. “Kiai Abdul Karim dan Nyai Mas Amirah sampai mengobrak-abrik pasukan Belanda di daerah yang kini dikenal sebagai Jalan KH. Abdul Karim, Gresik,” kisah KH. Munawwir. Namun, karena kalah jumlah, akhirnya beliau bersama Nyai Mas Amirah dan anak-anak beliau yang masih kecil-kecil, yaitu Muhammad Zahid, Ishaq, Maimunah, dan Shofiyah, ditangkap dan dipenjara di Surabaya.
Keluarnya KH. Abdul Karim dan keluarganya dari penjara bukanlah hal mudah. Ini berkat negoisasi yang dilakukan oleh Raden Jamilun, ayah dari Nyai Mas Amirah, dengan pimpinan Belanda pada masa itu. Kisah ini menjadi bukti nyata keteguhan keluarga ulama dalam mempertahankan prinsip dan agama di tengah tekanan penjajah.
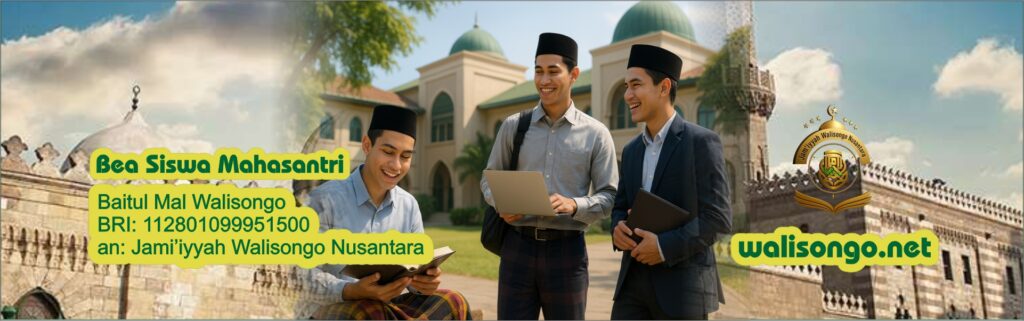
Setelah dibebaskan, KH. Abdul Karim menerima amanah untuk membina masyarakat Tebuwung Dukun Gresik, Jawa Timur. Pada tahun 1863, Pak Utsman/Warjo, Kepala Desa Tebuwung yang masih sepupu Nyai Mas Amirah, berinisiatif mencari seorang ulama untuk membina masyarakatnya. Melalui musyawarah dengan Nyai Mas Amirah dan KH. Abdul Karim, serta menghadap Adipati Sidayu, diputuskanlah bahwa KH. Abdul Karim akan membina masyarakat Tebuwung dan sekitarnya yang kala itu masih menganut Kapitayan, Hindu, dan Buddha.
Untuk mendukung misi dakwah ini, Pak Utsman dan keluarganya bersepakat untuk mewakafkan tanah di bagian Timur Desa Tebuwung kepada KH. Abdul Karim. Para dermawan yang turut serta memberikan tanah tersebut antara lain:
Di tanah wakaf inilah kemudian KH. Abdul Karim bersama keluarga mulai mendirikan musholla dan pesantren. Selama masa awal pembangunan ini, KH. Abdul Karim sekeluarga sering melakukan tirakat puasa mutih, sebuah bentuk riyadhah spiritual yang kuat untuk memohon keberkahan dan kemudahan dalam menghadapi tantangan dakwah yang berat.
“Ketika pesantren dilanda kesulitan finansial akibat paceklik, Nyai Mas Amirah-lah yang berinisiatif kembali berdagang garmen untuk menggerakkan perekonomian pesantren,” tambah KH. Munawwir. “Bahkan, beliau tak segan-segan pulang pergi Tebuwung-Sidayu dengan menaiki kuda, memastikan pasokan barang dagangan dan mendukung penuh kebutuhan pesantren. Ini adalah pengorbanan luar biasa dari seorang cucu Bupati dan trah bangsawan yang bersemangat juang.”
Hasil keuntungan dari bisnis garmen Nyai Mas Amirah digunakan sepenuhnya untuk pesantren dan membantu masyarakat yang kekurangan. Bahkan, demi keberlangsungan dakwah, beliau dengan ikhlas dan mulia merelakan Kiai Abdul Karim menikah lagi.
Setelah Kiai Abdul Karim menikah lagi. Nyai Amirah bertambah tekun mengajar di Pesantren dan masyarakat serta berbisnis di Sedayu. Tidak ada ceritanya kalau Nyai Mas Amirah tidak betah di Tebuwung. Beliau sangat menikmati Tebuwung karena sejak kecil, bersama ibunya ada di Tebuwung dan banyak keluarga beliau di Tebuwung, seperti Pak Warjo Sekeluarga.
Pengorbanan dan dedikasi Nyai Mas Amirah ini menunjukkan bahwa beliau adalah pilar penting dalam pendirian dan perkembangan Pondok Pesantren Tebuwung. Meskipun Nyai Mas Amirah wafat lebih dahulu pada tahun +1890 dan dimakamkan di komplek keluarga Kanjeng Sepuh Sidayu, semangatnya terus menginspirasi.
KH. Abdul Karim Tebuwung sendiri wafat pada hari Selasa Legi, 27 Dzulhijah 1313 H (9 Juni 1896), dalam usia 66 tahun, dan dimakamkan di Tebuwung, berdampingan dengan Petinggi Utsman. Estafet kepemimpinan pesantren kemudian dilanjutkan oleh putra beliau.
Pengganti KH. Abdul Karim Tebuwung adalah putra beliau, KH. Muhammad Zahid (lahir tahun +1858), yang pada saat itu berusia 38 tahun. KH. Muhammad Zahid melanjutkan perjuangan ayahnya hingga wafat pada hari Senin Pon, 13 Jumadil Akhir 1321 H (20 Mei 1913), dalam usia 55 tahun.
Jejak rekam keturunan KH. Abdul Karim Tebuwung dalam dunia pesantren sangatlah luar biasa. Banyak dari putra-putri dan cucu-cucu beliau yang mengikuti jejak langkahnya dalam berdakwah dan mendirikan lembaga pendidikan Islam di berbagai daerah, antara lain:
Haul ke-133 ini menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai kebersamaan dan pengorbanan yang dicontohkan oleh KH. Abdul Karim dan Nyai Mas Amirah, sebuah pasangan yang tak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga membangun pondasi peradaban melalui pendidikan dan keteladanan, yang kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh generasi penerus mereka. Wallahu’ Alam bishowab.
Pernahkah terlintas di benak kita, mengapa ada hari baik dan ada hari yang terasa kurang beruntung? Atau mengapa ada hari-hari tertentu yang terasa lebih berkah untuk aktivitas spesifik? Ternyata, jauh sebelum kita mengenal konsep “hari baik” dalam kalender modern, seorang ulama besar dan waliyullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, telah mengulas secara mendalam rahasia dan keutamaan hari-hari dalam seminggu.
Dalam karyanya yang monumental, Kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haqqi ‘Azza wa Jalla (Bekal bagi Pencari Jalan Kebenaran Yang Maha Agung lagi Maha Perkasa), beliau menjelaskan berbagai kejadian penting dan amalan yang dianjurkan berdasarkan hari-hari. Penjelasan ini bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan riwayat para sahabat. Mari kita telusuri hikmah di baliknya!
Hari Penciptaan: Mengenal Jejak Allah di Setiap Hari
Salah satu riwayat menarik yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah tentang proses penciptaan alam semesta dan Adam ‘alaihis salam. Beliau mengutip hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “خَلَقَ اللَّهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ فِيهَا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَخَلَقَ الْخَيْرَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ آخِرَ خَلْقٍ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ.”
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Allah Ta’ala menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan gunung-gunung padanya pada hari Ahad, menciptakan pepohonan pada hari Senin, menciptakan hal yang dibenci pada hari Selasa, menciptakan kebaikan pada hari Rabu, menyebarkan binatang melata padanya pada hari Kamis, dan menciptakan Adam ‘alaihis salam setelah Ashar pada hari Jumat, sebagai ciptaan terakhir pada saat terakhir dari jam-jam Jumat, antara Ashar hingga malam.”
Riwayat ini memberikan kita gambaran tentang kekuasaan dan ketelitian Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Setiap hari memiliki “tanda” penciptaan-Nya, mengingatkan kita akan kebesaran-Nya.
Karakteristik Hari: Memahami Makna di Balik Setiap Tanggal
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengutip riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu yang menjelaskan karakteristik unik setiap hari berdasarkan peristiwa bersejarah dan petunjuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam:
قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: “يَوْمُ السَّبْتِ يَوْمُ مَكْرٍ وَخَدِيعَةٍ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ قُرَيْشًا تَآمَرَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِ النَّدْوَةِ.”
Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata: “Hari Sabtu adalah hari tipu daya dan pengkhianatan. Dinamakan demikian karena kaum Quraisy bersekongkol melawan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam di Darun Nadwah pada hari itu.” Ini jadi pengingat untuk senantiasa waspada dan memohon perlindungan dari tipu daya.
وَيَوْمُ الْأَحَدِ يَوْمُ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ وَهُوَ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ الدُّنْيَا وَبَنَاهَا
Dan hari Ahad adalah hari menanam dan membangun, dan pada hari itu adalah awal mula Allah menciptakan dunia dan membangunnya.” Cocok untuk memulai proyek baru atau menanam kebaikan.
“وَيَوْمُ الِاثْنَيْنِ يَوْمُ سَفَرٍ وَتِجَارَةٍ سَافَرَ فِيهِ نَبِيُّ اللَّهِ شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاتَّجَرَ
“Dan hari Senin adalah hari perjalanan dan perdagangan. Nabi Syu’aib ‘alaihis salam melakukan perjalanan dan berdagang pada hari ini.” Ini bisa jadi motivasi untuk melakukan perjalanan yang bermanfaat atau memulai usaha.
“وَيَوْمُ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ، حَاضَتْ فِيهِ حَوَّاءُ وَقَتَلَ ابْنُ آدَمَ أَخَاهُ فِيهِ
“Dan hari Selasa adalah hari darah. Siti Hawa mengalami haid pada hari itu, dan putra Adam membunuh saudaranya pada hari itu.” Ada pelajaran tentang takdir dan ujian yang menyertai kehidupan.
“وَيَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ وَشُؤْمٍ، غَرِقَ فِيهِ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، وَهَلَكَ فِيهِ قَوْمُ عَادٍ وَثَمُود
“Dan hari Rabu adalah hari nahas dan kesialan. Pada hari ini Firaun dan kaumnya ditenggelamkan, serta kaum Ad dan Tsamud dibinasakan pada hari ini.” Ini mengingatkan kita akan bahaya kesombongan dan kekufuran.
وَيَوْمُ الْخَمِيسِ يَوْمُ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَلِقَاءِ السُّلْطَانِ لَقِيَ فِيهِ نَبِيُّ اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَمْرُودَ وَقُضِيَتْ حَاجَتُهُ
Dan hari Kamis adalah hari penunaian hajat dan bertemu penguasa. Nabi Ibrahim ‘alaihis salam menemui Namrud dan hajatnya terpenuhi pada hari ini.” Ini bisa jadi momen baik untuk menyelesaikan urusan penting atau menyampaikan aspirasi.
وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ خُطْبَةٍ وَتَزْوِيجٍ زُوِّجَ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَنْبِيَاء
“Dan hari Jumat adalah hari khotbah dan pernikahan. Banyak dari para Nabi menikah pada hari ini.” Tentu, ini menguatkan posisi Jumat sebagai hari berkah untuk ibadah dan momen sakral seperti pernikahan.
Amalan Pilihan di Hari-Hari Tertentu
Selain karakteristik di atas, Kitab Al-Ghunyah juga memuat beberapa anjuran amalan yang bisa kita praktikkan:
“إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تُفْتَحُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ.”
“Sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan hari Kamis, maka diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali seseorang yang di antara dia dan saudaranya ada permusuhan.
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ صَوْمَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ فِيهِمَا.”
“Adalah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tidak pernah meninggalkan puasa pada hari Senin dan Kamis, karena amal perbuatan dipaparkan pada kedua hari tersebut.” Ini adalah kesempatan emas untuk memohon ampunan dan membersihkan diri.
“مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً: الْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ جَوْهَرٍ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ.”
Terjemahan: “Barang siapa yang berpuasa tiga hari berturut-turut: Rabu, Kamis, dan Jumat, niscaya Allah akan membangunkan istana di surga dari permata dan membebaskannya dari api neraka.” Sungguh pahala yang luar biasa!
مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الْحُرُمِ: الْخَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ كُتِبَ لَهُ عِبَادَةُ تِسْعِمِائَةِ سَنَةٍ.”
“Barang siapa yang berpuasa tiga hari dari bulan-bulan haram: Kamis, Jumat, dan Sabtu, maka akan ditulis baginya pahala ibadah sembilan ratus tahun.” (Bulan Haram adalah Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab).
الْحِجَامَةُ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِسَبْعَةَ عَشَرَ تُذْهِبُ دَاءَ سَنَةٍ.
“Berbekam pada hari Selasa tanggal tujuh belas dapat menghilangkan penyakit selama setahun.” Ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kesehatan dan waktu yang tepat untuk melakukan pengobatan.
Keistimewaan Jumat: Hari Agung Milik Allah dan Umat Muhammad
Dan puncaknya adalah hari Jumat. Meskipun setiap hari memiliki kekhasan, hari Jumat memiliki tempat tersendiri. Dikatakan bahwa hari ini adalah milik Allah ‘Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam:
يَا مُحَمَّدُ الْجُمُعَةُ لِي وَالْجَنَّةُ لِي فَقَدْ جَعَلْتُ الْجُمُعَةَ لِأُمَّتِكَ وَالْجَنَّةَ مَعَهَا وَأَنَا مَعَ الْجُمُعَةِ وَالْجَنَّةِ لِأُمَّتِكَ.”
“Wahai Muhammad, Jumat adalah milik-Ku dan Surga adalah milik-Ku. Maka Aku berikan Jumat kepada umatmu dan Surga bersamanya, dan Aku bersama Jumat dan Surga untuk umatmu.”
Ini adalah karunia terbesar bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Hari Jumat bukan hanya tentang shalat Jumat, tetapi juga tentang keberkahan yang Allah limpahkan khusus untuk kita, umat terakhir.
Kesimpulan
Melalui warisan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Al-Ghunyah, kita diajarkan untuk tidak memandang hari-hari secara biasa saja. Setiap hari adalah anugerah dan mengandung potensi kebaikan atau peringatan. Dengan memahami rahasia di balik setiap hari, kita bisa lebih bijak dalam menjalani hidup, mengoptimalkan waktu untuk beribadah, berinteraksi, dan meraih keberkahan.
Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari khazanah ilmu ini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam kehidupan ini, mengenal Allah adalah fondasi utama bagi seorang mukmin. Interaksi kita dengan-Nya bukan sekadar rutinitas ibadah, melainkan sebuah perjalanan hati yang penuh ketakwaan, kepercayaan, rasa syukur, dan keikhlasan. Mari kita selami lebih dalam hakikat interaksi dengan Sang Pencipta, sebagaimana dinasihatkan oleh seorang ahli hikmah yang diriwayatkan dalam kitab Adabun Nufus karya Al-Harits Al-Muhasibi, halaman 35-38, yang diterbitkan oleh Dar al-Jail, Beirut, Lebanon.
Sang ahli hikmah memulai nasihatnya dengan seruan universal: “Saya menasihati Anda dan diri saya, dan siapa pun yang mendengar perkataan saya, untuk bertakwa kepada Allah, Yang menciptakan hamba-hamba-Nya, kepada-Nya tempat kembali, dan dengan-Nya ada kebenbasan dan petunjuk.”
Bertakwa kepada Allah berarti memahami kedekatan-Nya dan kekuasaan-Nya atas diri kita. Ini adalah takwa yang lahir dari kesadaran bahwa Dia senantiasa bersama kita, mengetahui setiap gerak-gerik dan bisikan hati. Keimanan kita kepada-Nya haruslah iman orang yang mengakui keesaan-Nya, keunikan-Nya, dan keazalian-Nya. Bukti-bukti keesaan-Nya begitu nyata: dari keindahan kerajaan-Nya yang terhampar di alam semesta, hingga kesempurnaan ciptaan-Nya yang tiada cela. Ayat-ayat dan dalil-dalil yang tak terhitung jumlahnya membuktikan ketuhanan-Nya, ketetapan kehendak-Nya, serta kebaikan pengaturan-Nya. Segala ciptaan dan perintah adalah milik-Nya, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.
Setelah takwa, pilar berikutnya adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah. Ini adalah kepercayaan orang yang berprasangka baik kepada-Nya, tanpa ada sedikit pun keraguan atau kecurigaan. Orang yang percaya sepenuhnya akan membenarkan janji-Nya, yakin akan jaminan-Nya, dan hatinya akan merasakan ketenangan dari segala kegelisahan. Dalam hati mereka, ancaman Allah terasa agung, mendorong mereka untuk senantiasa berhati-hati.
Bersamaan dengan kepercayaan, rasa syukur menjadi bagian tak terpisahkan. Syukuri Allah seperti orang yang telah memahami betapa besar karunia-Nya, betapa banyak pemberian-Nya, dan kebaikan-Nya yang tiada henti. Renungkanlah nikmat-nikmat-Nya yang lahir dan batin, yang bersifat khusus maupun umum.
Inti dari setiap ibadah dan amal adalah keikhlasan. Ikhlaslah kepada Allah seperti orang yang tahu bahwa Dia tidak akan menerima amal kecuali jika bersih dari segala cacat dan semata-mata dilakukan karena Allah, tanpa ada sekutu. Ini berarti tidak menyekutukan seorang pun dalam amal kita selain Dia.
Peringatan penting di sini adalah tentang riya’ atau menyekutukan makhluk dalam beramal. Ini terjadi ketika seseorang berhias diri di hadapan manusia saat melakukan kebaikan, berdusta dalam amalnya, atau berbuat riya agar dihormati dan diagungkan. Ia mungkin mencari pujian atas perkataannya yang indah atau kebaikan yang tampak dari amalnya, entah ia sadar atau tidak.
Tidak ada yang selamat dari keburukan riya’ kecuali orang yang menjauhinya dan beramal tanpa keinginan diketahui oleh makhluk. Jika pun ada yang mengetahui amalnya tanpa ia inginkan, maka keikhlasannya teruji dari ketidaksukaannya terhadap pujian atas amal tersebut. Jika ia dipuji namun tidak menyukainya, janganlah ia merasa senang. Dan jika ia merasa senang, janganlah kesenangan itu karena tujuan duniawi.
Kejujuran dalam perkataan dan perbuatan adalah cerminan dari kesadaran bahwa Allah mengetahui setiap inci dari diri kita: yang tersembunyi, yang rahasia, yang terang-terangan, dan bahkan apa yang tersimpan dalam hati.
Kemudian, bertawakallah kepada Allah sebagaimana tawakal orang yang percaya sepenuhnya pada janji-Nya dan merasa tenteram dengan jaminan-Nya. Tawakal ini lahir dari keyakinan akan kesetiaan-Nya, keridaan terhadap takdir-Nya, penyerahan diri pada perintah-Nya, keimanan akan takdir-Nya, serta keyakinan yang tulus akan surga dan neraka-Nya.
Takut kepada Allah adalah rasa takut yang muncul dari pemahaman akan keperkasaan-Nya, kerasnya siksaan-Nya, azab-Nya yang pedih, serta dampak dan balasan bagi siapa pun yang melanggar perintah-Nya dan durhaka kepada-Nya. Ketahuilah bahwa tidak ada penolong bagi yang Dia tinggalkan, dan tidak ada kebaikan yang mampu menandingi bimbingan, perlindungan, dan penjagaan-Nya. Tak ada yang mampu bersabar menghadapi siksaan dan hukuman-Nya, serta perubahan nikmat-nikmat-Nya.
Namun, rasa takut ini harus diimbangi dengan harapan kepada Allah. Harapkanlah Dia seperti orang yang membenarkan janji-Nya dan telah melihat pahala-Nya. Syukurilah Dia seperti orang yang diterima kebaikannya, diperbaiki amalnya, dan dianugerahi dari limpahan karunia serta kemuliaan-Nya yang melebihi apa yang layak ia dapatkan.
Rasa malu kepada Allah adalah malu yang timbul dari kesadaran akan begitu banyaknya karunia dan pemberian-Nya, sementara kita menyadari kekurangan diri dalam bersyukur, sedikitnya kesetiaan pada janji-Nya, dan ketidakmampuan menunaikan hak-Nya. Meski demikian, kita senantiasa merasakan keindahan penutupan aib-Nya, keagungan keselamatan, berlanjutnya nikmat, kebaikan-Nya yang terus-menerus, kesabaran-Nya yang luar biasa, dan pemaafan-Nya.
Akhirnya, ingatlah bahwa Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban yang tampak dan tersembunyi. Dia telah menetapkan syariat-syariat yang ditunjukkan kepada kita dan diperintahkan untuk kita laksanakan. Dia menjanjikan pahala besar bagi yang melaksanakannya dengan baik, dan mengancam dengan siksaan pedih bagi yang melalaikannya. Ini semua adalah rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita.
Maka, laksanakanlah kewajiban-kewajiban-Nya, patuhilah syariat-syariat-Nya, ikutilah sunah Nabi ﷺ, serta teladanilah jejak para sahabat Nabi. Hiasi diri dengan adab-adab mereka, ikuti jalan mereka, dan jadikan petunjuk mereka sebagai pedoman. Berwasilah kepada Allah dengan mencintai mereka dan mencintai siapa pun yang mencintai mereka, karena merekalah orang-orang yang kembali kepada-Nya, menuju tujuan-Nya, dan dipilih oleh-Nya untuk menemani Nabi-Nya sebagai kekasih dan sahabat.
Semoga refleksi ini menginspirasi kita untuk senantiasa memperbaiki interaksi dengan Allah, demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.
“Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat.”
— Imam Malik
Nama Fatimah binti Muhammad al-Fihriya al-Qurasyiyah atau lebih dikenal dengan Fatimah al-Fihri, adalah simbol keagungan perempuan dalam sejarah peradaban Islam. Di saat perempuan dalam masyarakat Jahiliyah dipandang sebagai aib dan pelengkap semata, Islam hadir memuliakan mereka, dan Fatimah al-Fihri menjadi salah satu contoh nyata bagaimana perempuan Muslim bisa menjadi pelopor peradaban dunia.
Fatimah al-Fihri lahir sekitar tahun 800 M di kota Kairouan, wilayah yang kini dikenal sebagai Tunisia. Ia berasal dari keluarga Quraisy yang taat beragama dan menjunjung tinggi nilai pendidikan. Ayahnya, Muhammad al-Fihri, adalah saudagar sukses yang hijrah ke kota Fez, Maroko, untuk memperluas jaringan usaha.
Keluarga al-Fihri dikenal dermawan dan memiliki kepedulian besar terhadap ilmu. Bersama saudarinya, Maryam, Fatimah tumbuh sebagai perempuan berilmu, berakhlak luhur, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.
Setelah wafatnya ayah dan suaminya, Fatimah mewarisi kekayaan besar. Namun, bukan kekayaan yang menjadi kebanggaannya. Ia justru menginfakkan seluruh hartanya untuk membangun sebuah masjid dan madrasah di kawasan komunitas Qarawiyyin di Fez. Masjid itu dibangun pada Ramadhan tahun 245 H / 859 M dan diberi nama Jami’ al-Qarawiyyin.
Fatimah melaksanakan pembangunan masjid tersebut dengan penuh ketakwaan dan kesungguhan spiritual, bahkan disebutkan ia berpuasa selama proses pembangunan berlangsung, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah.
Awalnya, Al-Qarawiyyin adalah masjid tempat ibadah dan diskusi ilmiah masyarakat. Namun seiring waktu, aktivitas keilmuan berkembang pesat hingga menjadikannya sebagai madrasah terbesar, dan kemudian universitas Islam pertama di dunia.
Universitas Al-Qarawiyyin tidak hanya menjadi pusat studi Islam, tetapi juga menjadi jembatan keilmuan antara dunia Islam dan Barat. Di bawah Dinasti Murabithun dan Dinasti Bani Marin, madrasah ini resmi menjadi universitas dan melahirkan banyak tokoh dunia.
Perpustakaannya, yang didirikan oleh Sultan Abu-Annan dari Dinasti Marinid, menyimpan berbagai karya besar, seperti:
Al-Qarawiyyin mencetak ulama dan cendekiawan besar lintas zaman dan agama, antara lain:
Pada tahun 1998, Guinness Book of World Records menetapkan Al-Qarawiyyin sebagai universitas tertua di dunia yang masih aktif dan menawarkan gelar akademik.
Majalah TIME edisi 24 Oktober 1960 menyebutkan bahwa universitas ini mendorong kebangkitan intelektual di Eropa abad ke-15 M. Melalui para lulusannya, konsep angka Arab dan sistem desimal tersebar ke dunia Barat, menggantikan angka Romawi.
Perjuangan Fatimah al-Fihri menjadi inspirasi besar bagi perjuangan pendidikan umat Islam masa kini. Ia membuktikan bahwa perempuan tidak hanya berhak belajar, tapi juga berhak menjadi pelopor, pendidik, dan pendiri lembaga ilmu yang kekal hingga generasi ke generasi.
Bagi Jam’iyyah Walisongo Nusantara dan pegiat dakwah pendidikan seperti di situs walisongo.net, kisah Fatimah al-Fihri adalah bukti bahwa wakaf ilmu dan amal jariyah melalui pendidikan mampu mengubah sejarah. Semangat ini sejalan dengan visi Walisongo dalam mencetak generasi unggul dan meneruskan dakwah global.
Fatimah al-Fihri bukan hanya seorang tokoh perempuan. Ia adalah arsitek peradaban ilmu, pendiri madrasah tertua di dunia, dan pelita yang menyinari gelapnya zaman dengan cahaya ilmu dan ketakwaan.
“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”
— (HR. Muslim)